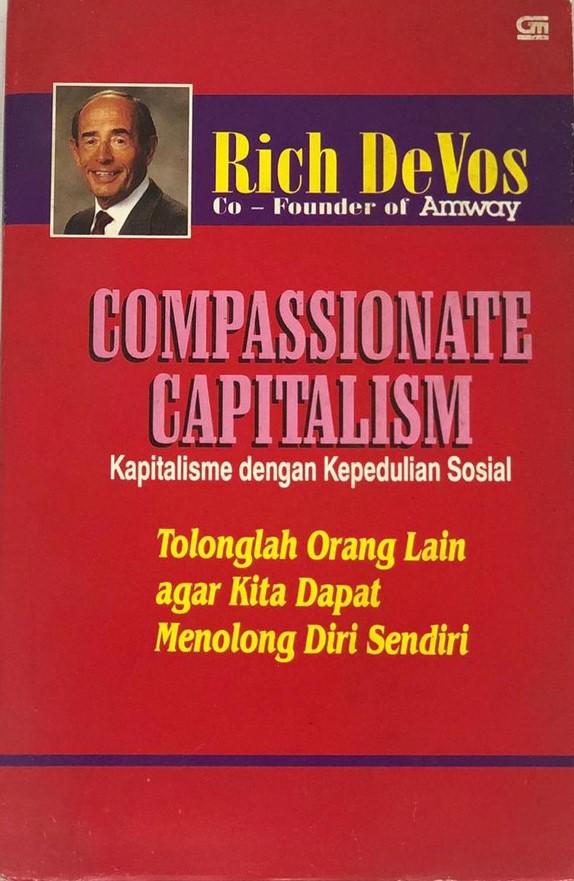Judul: Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi
Judul: Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi
Penulis: R. Sri Soemantri M.
Penerbit: P.T. Alumni, Bandung
Edisi: Kedua
Cetakan: Pertama, 2006
Tebal: xx + 482 halaman
ISBN: 979-414-023-6
Mengapa buku ini penting dibahas, setidaknya dilatari dua alasan strategis. Pertama terkait wacana amandemen konstitusi yang kembali mengemuka (terutama dalam hal kewenangan dewan perwakilan daerah). Kedua sebagai refleksi atas amandemen empat kali yang kemudian menimbulkan polemik pemaknaan semantik (terkait rumusan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945).
Buku prosedur dan sistem perubahan konstitusi pada awalnya merupakan disertasi R. Sri Soemantri M. Sehingga sebagai sebuah karya akademik, dipenuhi banyak referensi dan keterangan tambahan. Kekayaan referensi demikian menjadikan buku ini sangat layak dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan konstitusional, dalam artian bagaimana etiknya amandemen dilakukan.
Buku ini pertama kali dicetak pada tahun 1978, masa ketika konstitusi betul-betul disakralkan, bahkan dogma yang tabu untuk diopinikan, apalagi diubah. Maka keistimewaan buku ini justru terletak pada dimensi historis yang menjadi latar waktu penulisannya. Selain tentu saja, studi komparasi yang melihat konstitusi Indonesia dalam perpektif sistem hukum. Bagaimana prosedur perubahan konstitusi dilakukan dalam satu kesatuan pemikiran hukum.
Secara historis, UUD 1945 lahir dalam masa penuh pergolakan global. Ketika gerakan dekolonisasi di pertengahan abad ke-20 mencapai puncaknya, dengan gagasan-gagasan yang penuh perlawanan dan semangat kebebasan, konstitusi Indonesia dilahirkan. Masa kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang juga menjadi salah satu faktor penting yang perlu ditilik dalam pembicaraan konstitusi.
Bahwa buku ini juga menarik sebab ditulis dengan beragam pendekatan, yakni historik, yuridik, komparatif, dan politik. Aspek historis tergambar dari uraian penulis mengenai dinamika kesejarahan pembentukan konstitusi, bagaimana realitas zamannya turut mempengaruhi perkembangan konstitusi. Yuridik, sebab kajian ini termasuk dalam rezim hukum tata negara. Aspek komparatif dikaitkan dengan realitas perubahan konstitusi di berbagai negara, dalam hal ini yang menjadi perbandingan yaitu konstitusi Kerajaan Belanda, Amerika Serikat, dan Sovyet Uni. Dan politik karena menyangkut konstelasi aspirasi perubahan, apakah merupakan produk politik atau produk hukum.
Dalam kalimat awal, penulis menyajikan ungkapan dialektis, apakah generasi lalu mengikat generasi sekarang, sehingga dalam konteks hari ini, apakah generasi sekarang mengikat generasi mendatang? Ungkapan yang menjadi pangkal paradigma amandemen, sekaligus pertanyaan mendasar mengapa buku ini ditulis.
Dialektis
Adanya rumusan (kemungkinan) perubahan konstitusi adalah manifestasi dinamik pemahaman bernegara para perumus. Walau tema perubahan tidak begitu diskursif dalam proses perumusan, wacana tersebut akhirnya “mengimbuhi” materi muatan konstitusi. Sempat pula tidak diseriusi, usulan salah seorang anggota BPUPK (S. Kolopaking) baru mendapat tanggapan dalam sidang PPKI, setelah wacana serupa dilontarkan Iwa Kusumasumantri, dan praktis diterima tanpa perdebatan alot.
Terkait konsep perubahan tersebut, perdebatan kemudian berkisar prosedur (teknis legitimasi). Anggota A. Subardjo mengusulkan perubahan yang mudah (diterima dengan suara terbanyak dari minimal 2/3 yang hadir), yang segera mendapat tentangan (terutama) oleh Ki Bagus Hadikusumo (sesuai perumusan awal oleh Soepomo, yakni minimal 2/3 dari minimal 2/3 yang hadir). Akhirnya, usulan terakhir yang kemudian mewujud dalam materi muatan konstitusi.
Setelah dibanding konstitusi tiga negara (yang juga merepresentasi bermacam sistem hukum), konstitusi Indonesia termasuk dalam klasifikasi rigid. Disebut demikian karena, pertama mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Kedua hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa.
Menyikapi ciri tersebut, peresensi sepakat bahwa UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi. Hal ini—kalau meminjam Hans Kelsen—disebut sebagai fundamental norm (norma fundamental). Dalam teori jenjang norma hukum Kelsen (Stufenbau theory), konstitusi menduduki puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal perubahan, tentu saja akan berdampak pada keberbedaan prosedur dibanding peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga menjadi masuk akal melalui proses yang istimewa/ tidak mudah.
Dimungkinkannya perubahan atas konstitusi juga perlu memperhatikan landasan filosofis tentang konstitusi itu sendiri. Sebagai dokumen formal (sebab dituangkan dalam tulisan), UUD 1945 adalah hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan para tokoh bangsa yang hendak diwujud, serta suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan kenegaraan bangsa hendak dipimpin. Maka dengan sendirinya, wacana perubahan selalu perlu ditimbang matang. Dalam bahasa peresensi, jangan sampai dinamika zaman menista terlalu jauh idealitas romantik.
Ideologis?
Wacana amandemen kelima harus dikaji mendalam, tidak saja terkait materi muatannya, namun juga amanat zaman tatkala konstitusi dirumuskan.
Membaca UUD awal (istilah ini mengacu konstitusi pra amandemen) bagai menelisik mozaik pemikiran pendiri bangsa. Perdebatan panjang antara Soekarno, Soepomo, Hatta, dan Muhammad Yamin adalah manifes konsep dasar bagaimana negara ini dikelola. Wacana-wacana seputar politik, ekonomi, sosial demokrasi, bergelayut dinamis.
Secara kasat bagai pertarungan tradisionalisme versus modernisme, konservatisme dengan progresifisme. Di satu sisi Soekarno dan Soepomo mengimpikan Indonesia merdeka dibangun di atas altar kegotong-royongan dan bertendensi paternalistik, sementara Hatta Dan Yamin lebih bergairah menyuntikkan pemikiran demokrasi, ekonomi pemerataan, dan humanisme sosial.
Dari gambaran di atas, peresensi ingin menyatakan bahwa perdebatan materi muatan berangkat dari akar ideologisnya, yang berlandas nasionalisme, politik demokrasi, dan ekonomi bertumpu peran negara. Sebagai hasilnya, terang terlihat dalam konstitusi awal, bagaimana imaji para pendiri bangsa mewujud.
Maka amandemen yang telah terjadi, dengan penambahan unsur “efisiensi” di samping “kebersamaan”, berkeadilan”, dan “kemandirian” adalah cermin paradoks. Demikian karena di satu sisi kental dengan gagasan-gagasan liberalisme ekonomi, sementara di sisi lain, bernuansa sosialisme kerakyatan. Sehingga Pasal 33 ayat 4 ini sangat rawan dijustifikasi untuk kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu. Selain tentu saja akan menimbulkan tumpang tindih dalam tata desain kebijakan pembangunan nasional.
Pun demikian halnya dengan wacana penambahan kewenangan dewan perwakilan daerah (DPD), menyisakan tanda tanya baru. Kecurigaan yang muncul tentunya terkait perubahan bentuk negara, sebab –walaupun bukan ciri utama- akan menjadi pintu masuk ke arah bentuk federalisme. Boleh saja menyatakan penambahan kewenangan tersebut hanyalah strategi pengaturan aspirasi terkait besar kecil daerah dan jumlah penduduk, namun praktek tersebut lazimnya dikenal dalam negara-negara federal.
Oleh karenanya, buku prosedur dan sistem perubahan konstitusi ini niscaya kehadirannya menjadi acuan teoritik tentang bagaimana memandang konstitusi dan beragam dinamika bernegara yang mucul kemudian. Selamat membaca!
Arifuddin Hamid
Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia
UI, Depok, 9 Desember 2011