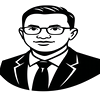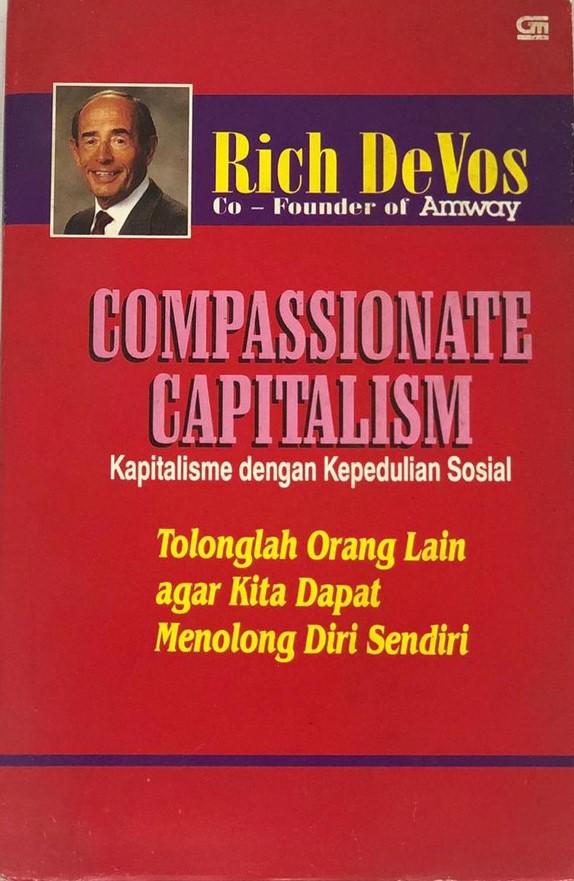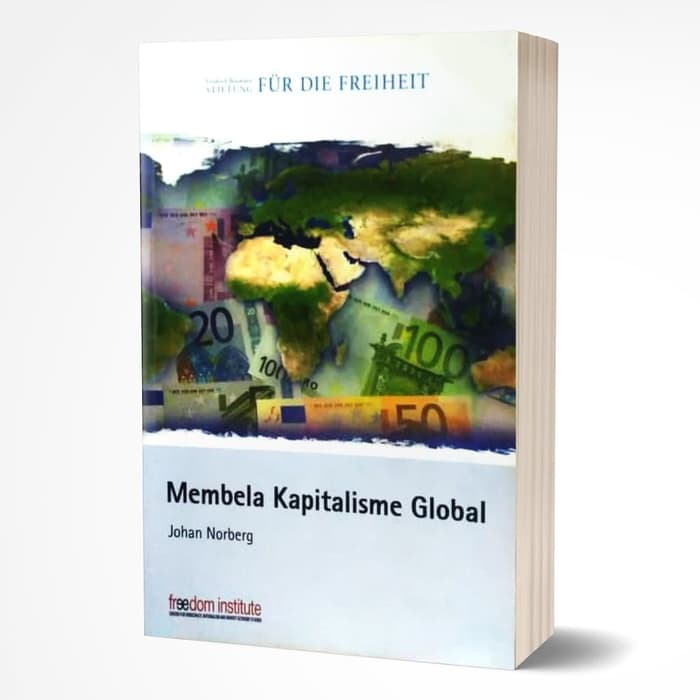 Judul: Membela Kapitalisme Global
Judul: Membela Kapitalisme Global
Penulis: Johan Norberg
Penerjemah: Arpani dan Sukasah Syahdan
Penerbit: Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit, Indonesia dan The Freedom Institute
Cetakan: Pertama, 2008
Tebal: xxx+342 hal
ISBN: 978-979-1157-16-2
Membuat ulasan atas sebuah buku terkadang bukan pekerjaan sepele, apalagi dimaksudkan sebagai sebuah ulasan kritis. Terlebih buku yang dalam Bahasa Swedia berjudul asli Till världskapitalismens försvar ‘Membela Kapitalisme Global’ ini, mengupas wacana yang bisa dikategorikan berat dan serius. Ketidaksepelean ini semakin terlihat oleh substansi buku yang mengulas banyak isu, dari isu besar tentang kemiskinan sampai lingkungan, kebebasan berusaha sampai modal internasional, bahkan dalam tataran lebih spesifik mengenai unsur-unsur subjektif dan konspirasi elite dalam penetapan tarif dan bea masuk barang/jasa. Dengan luasnya cakupan isu, maka buku ini menjadi pantas untuk disebut sebagai bacaan pembela kapitalisme global yang teguh, dengan gaya tutur yang menohok dan berterus terang.
Kelebihan buku ini terletak pada pemaduan antara kekayaan statistika dengan bahasan teoritis yang terkadang filsafati. Dalam beberapa bab awal, buku ini cenderung memaparkan data dan angka statistik, hal mana yang sedikit berbeda dengan pengungkapan pada beberapa bab terakhir. Yang menarik, penggunaan statistika ini tidak terkesan membosankan, setidaknya bagi pembaca awam. Hal ini disebabkan penggunaan statistika oleh Norberg semata sebagai argumen pendukung, bukan statistika untuk tulisan itu sendiri.
Keapikan tulisan Norberg juga terlihat dari kemampuannya meramu berbagai doktrin penelitian lain guna mendukung bangunan argumentasinya. Hal ini misalnya terlihat dari pengutipannya atas Amartya Sen ―ekonom peraih Nobel dan pencetus konsep Human Development Index ‘indeks pembangunan manusia’, bahwa kemiskinan bukan semata masalah materi. Kemiskinan sesuatu yang lebih luas, dia juga tentang ketidakberdayaan, tentang terlucutinya kesempatan yang mendasar serta kebebasan untuk memilih. Pendapatan rendah seringkali gejala bagi hilangnya hal-hal tersebut, juga bagi marjinalisasi seseorang atau ketidakberdayaannya terhadap koersi (h. 12).
Dalam buku ini, Norberg banyak mencoba mematahkan berbagai persepsi umum yang ternyata jauh dari kenyataan. Misalnya terkait keberadaan aturan dalam ekonomi kapitalis. Banyak pihak yang percaya, bahwa kapitalisme menegasi aturan. Padahal justru sebaliknya. Menurut Norberg, bahkan dalam kapitalisme yang paling liberal sekalipun, memprasyaratkan keberadaan seperangkat aturan (h. 59), terlebih utama adalah aturan mengenai perlindungan terhadap hak milik, yang sekaligus merupakan jantung kapitalisme (h. 56).
Kekeliruan lain yang coba dijelaskan Norberg adalah tentang ketimpangan pendapatan. Pihak yang menisbatkan kapitalisme global sebagai pemicu ketimpangan seringkali bersikap tidak adil. Kenyataannya, tingkat pendapatan perkapita negara miskin meningkat signifikan setelah terjalinnya perdagangan global, walaupun memang negara kaya juga meningkat pendapatan perkapitanya. Mengenai hal ini, dalam nada reflektif Norberg menguraikan, bahwa jika standar hidup yang lebih baik layak diperjuangkan, maka yang penting adalah seberapa baik hidup anda, titik. Bukan seberapa baik hidup anda dalam perbandingannya dengan orang lain (h. 79). Terkait hal ini, dalam penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey Sachs dan Andrew Warner (1995), perekonomian miskin yang terbuka telah tumbuh lebih cepat daripada ekonomi kaya yang terbuka.
Norberg juga tampaknya tidak sebatas melakukan persuasi tentang keunggulan kapitalisme. Bahkan dalam alinea berikutnya, justru banyak melakukan sanggahan terhadap persepsi keliru yang kadung dipercaya publik. Keraguan yang kerap diungkap misalnya, jika perdagangan bebas terus-menerus membuat produksi semakin efisien, bukankah itu akan menyebabkan lenyapnya peluang kerja? (h. 147). Faktanya, peluang kerja justru bertambah, bahkan ini terjadi di negara Amerika Serikat yang merupakan negara paling kapitalistik. Lebih lanjut Norberg, sejak zaman praindustrial, penemuan-penemuan baru akan mendorong terciptanya lapangan kerja yang baru, begitu pun dengan perkembangan teknologi hari ini.
Kritik lain yang juga kerap terlontar, ternyata 20 persen persen populasi dunia mengonsumsi lebih dari 80 persen sumber daya bumi, sementara 80 persen populasi mengonsumsi kurang dari 20 persen. Mengenai hal ini, Norberg tidak berusaha membantah, bahkan setuju. Namun Norberg menyajikan penjelasan lain, bahwa 20 persen populasi yang mengonsumsi 80 persen sumber daya merupakan negara kaya adalah wajar, sebab 20 persen tersebut memproduksi 80 persen sumber daya, pun sebaliknya.
Sisi Lain Kapitalisme
Diakui Norberg, kapitalisme global ternyata tidak kebal kritik, dan dalam beberapa hal tertentu, aib. Aib ini terlihat dari penjelasan Norberg pada Bab IV buku ini (h. 172-180). Kenyataannya, yang juga dikritik cukup keras oleh Norberg, realitas perdagangan global tidak seajeg konsep kapitalisme yang digambarkan di buku-buku. Negara-negara kaya yang menjadi kampium kapitalisme justru memberlakukan pengenaan tarif dan pajak masuk yang tinggi untuk produk-produk tertentu dari negara berkembang, hal yang bertolak belakang dengan prinsipitas kapitalisme.
Realitas lain yang juga dikritik Norberg adalah kebijakan diskriminatif negara kaya terhadap negara miskin terkait perlindungan sosial dan lingkungan. Kebijakan ini ahistoris, bahkan belaka apologia oleh negara negara kaya. Kemestian perlindungan lingkungan dan buruh non-anak kepada negara miskin adalah kemusykilan. Dalam catatan sejarah, negara-negara yang sekarang disebut “kaya,” pada masa awal industrialisasi juga memperkerjakan buruh anak dan pabrik-pabriknya mencemari lingkungan. Jadi, bagaimana mungkin menyamakan standar industri di negara kaya dengan negara miskin?
Kritik introspektif Norberg tersebut memang tepat, namun belum cukup. Masih ada beberapa borok kapitalisme yang juga perlu mendapat perhatian dan sanggahan serius, termasuk yang dijelaskan Norberg dalam bab-bab akhir tulisannya. Terkait eksodus modal pada saat krisis Asia, Norberg tampaknya terlalu jauh melakukan simplifikasi. Misalnya terbaca dalam pengutipannya atas pendapat seorang investor, “sebuah pasar yang dulu punya andil hampir 18 persen pada sebagian besar dana, kini tidak dilirik sama sekali” (h. 291). Kebijakan pengetatan modal yang ditempuh Malaysia waktu itu, dalam berbagai literatur lain ―Tambunan, Memahami Krisis (2011) misalnya, justru mampu menyelamatkan Malaysia dari krisis. Dan fakta hari ini, Malaysia juga tetap dilirik oleh investor. Terkait hal ini, penjelasan Norberg terlalu linear dan struktulis, sebab ternyata pemerintahan dapat berganti, kebijakan relatif berubah.
Perkembangan terkini juga dapat menjadi pintu masuk kritik terhadap kapitalisme global. Deraan krisis tiada henti yang terjadi sejak tahun 2008 di Amerika Serikat yang efeknya berlanjut di Eropa, bahkan masih tersisa hingga kini, mestinya menjadi bahasan skenario oleh Norberg. Faktanya, bulir kecemasan ini pernah terjadi pada medio 1930-an, ketika dunia diterpa krisis global yang parah. Sayang sekali, Norberg tidak memaparkan persoalan ini. Terkait resesi yang terjadi, dapat diajukan beberapa preposisi kritis. Apakah resesi global, yang oleh banyak ekonom juga dinisbatkan pada keserakahan spekulan ―yang oleh Norberg terkait krisis Asia bukan menjadi kambing hitam utama― adalah bawaan orok yang menjadi kemestian diskursus praksis kapitalisme? Apakah demonstrasi besar-besaran para pengangguran di beberapa negara Eropa yang negaranya terancam bangkrut adalah bagian dari skenario kesejahteraan? Tampaknya Norberg perlu kembali meninjau beberapa bahasan, atau mungkin menambah penjelasan bukunya tentang pembelaannya akan kapitalisme global. Sebab kalau tidak, berbagai persoalan kasat yang dipertanyakan tersebut akan menjadi belief ‘kepercayaan’ ideologik, bahwa betapa kapitalisme global hanya unggul di atas kertas.
Meskipun buku ini semestinya lebih tepat disebut manifesto ideologik, sebab pembelaan Norberg tidak hendak dilihat secara teknis, melainkan paradigmatik, Norberg berusaha menggambarkan realitas secara objektif dan apa adanya. Oleh karenanya, buku ini patut menjadi kawan berdebat anda yang serius.
Arifuddin Hamid
Alumnus Fakultas Hukum UI
Jakarta, 1 Juli 2013