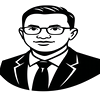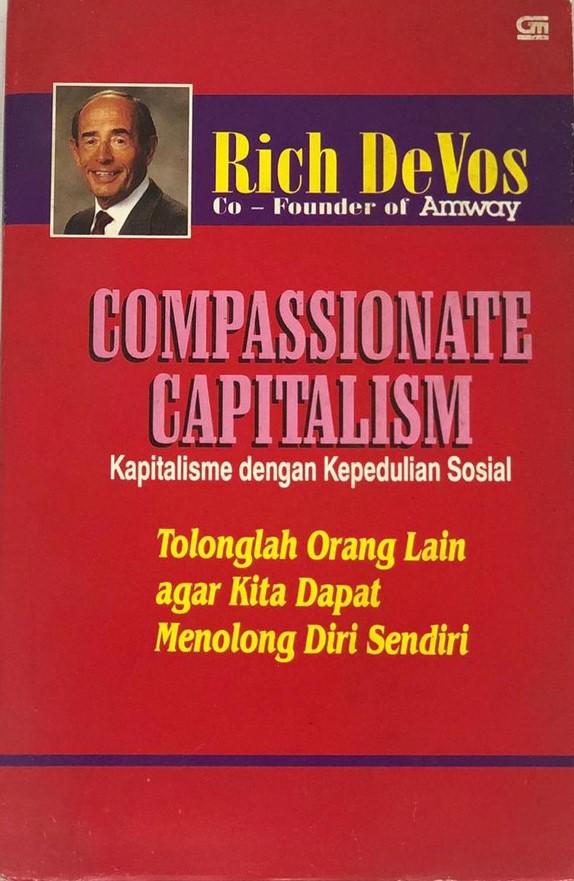Selain dilema menghadapi pandemi covid-19 yang nyaris membuat ekonomi Indonesia lumpuh, kabar duka yang kembali menyapa adalah penurunan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income) menjadi negara berpendapatan menengah rendah (lower middle income). Tidak salah kemudian banyak pihak yang menganggap jebakan negara berpendapatan menengah‘middle income trap (MIT) bukanlah mitos pembangunan, melainkan fakta ekonomi yang berimplikasi langsung pada nasab kemakmuran publik.
Sejatinya, optimisme mulai terlihat ketika pada 2016 silam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) disepakati dalam format perdagangan bebas regional. Indonesia adalah pemain utama di kawasan Asean sehingga diharapkan kerjasama ekonomi ini memberikan dampak mengganda bagi perekonomian. Alhasil, relasi kausal dan dilematis antara tantangan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), arah kebijakan menyikapi jebakan negara berpendapatan menengah, dan disparitas pembangunan menjadi wacana aktual kebangsaan. Ketiga variabel ini telah mengisi hampir sebagian besar wacana pembangunan selama sewindu terakhir.
Bagi Indonesia, postulat tersebut menjadi tantangan yang sangat pelik dan perlu diuji secara empirik. Maka itu, pertanyaannya: apakah kita akan berhasil melewati jebakan ini? Heston, Summers, dan Aten (2011) menemukan fakta bahwa dari seratusan negara yang diuji, hanya ada tiga belas negara yang berhasil melewati jebakan pendapatan pada tahun 2008. Meskipun pada 2010 silam Indonesia berhasil melewati rintangan, potensinya untuk terjebak MIT sangatlah besar (Felipe, 2010).
Optimisme Alamiah
Apakah Indonesia memang memiliki modalitas terhindar dari jebakan MIT, sekaligus menjejak sebagai negara berpendapatan tinggi (high income countries)?
Lajur Indonesia sejatinya sudah mulai terarah, yakni ketika pada awal 2020 mendapat status sebagai negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income) tatkala GNI per kapita Indonesia mencapai angka 4050 USD. Meski, hal ini sebenarnya tidaklah terlalu mengejutkan sebab ada beberapa studi prediktif yang mengurai optimisme. OECD (2009) dalam kajian bertajuk “Globalisation and Emerging Economies,” bahkan sempat menyebut akronim BRIICS untuk menggambarkan sekelompok negara yang memiliki kinerja pertumbuhan yang mengesankan, termasuk salah satunya Indonesia.
Bahkan jauh sebelumnya, Goldman Sachs (2007) meramalkan Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi kekuatan ekonomi ketujuh terbesar. McKinsey Global Institute (2012) juga dengan optimistik memprediksi Indonesia akan menempati posisi ekonomi terbesar ketujuh pada tahun 2030. Berbagai ramalan tersebut sejalan dengan portofolio PDB Indonesia yang mengalami perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan dalam kondisi kejatuhan harga komoditas global, kinerja perekonomian masih cukup tangguh.
Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada kenyataan potensial, dimana terdapat surplus penduduk usia muda. Dalam laporan Asian Development Bank (ADB, 2011) bertajuk “Asia 2050,” pada tahun 2025 nanti, Indonesia akan menjadi salah satu negara Asia yang akan menjadi penyangga utama kawasan. Karena itu, menurut ADB, perlu adanya produktivikasi sistemik angkatan kerja sehingga mampu bersaing dalam penciptaan produk baru guna menyongsong mimpi menjadi negara maju.
Disparitas
Di tengah upaya penyeragaman konsepsi di berbagai forum kebijakan dan akademik, pertanyaan pokok dan reflektif perlu diajukan: apakah MIT memang patut untuk dijadikan diskursus publik? Lalu, apakah komitmen peningkatan daya saing, konteks pembangunan infrastruktur, misalnya, sebatas kemestian pada ketercapaian inovasi dan produktivitas? Atau, apakah konsepsi ini tidak tidak harus mengaca dan determinis pada disparitas kewilayahan?
Pasalnya, realisasi kinerja pembangunan di pusat dan daerah begitu timpang. Visi akselerasi yang dicanangkan pemerintah tidak disambut semestinya oleh pemerintah daerah, sehingga berimplikasi pada telatnya pelaksanaan berbagai rencana pembangunan yang ada. Di akhir Juni 2021, dana pembangunan daerah yang mengendap di bank masih berjumlah sangat besar, yakni Rp190 triliun. Padahal, pemerintah pusat sudah berulang kali menegakkan kebijakan fiskal prodaerah melalui porsi alokasi dana perimbangan dan dana desa yang menaik setiap tahunnya.
Karena itu, tidaklah mengherankan jika terjadi gagap pertumbuhan, sekaligus menyempitnya realisasi pembangunan. Secara postulat, salah satu instrumen meningkatkan pertumbuhan adalah melalui ekspansi belanja publik. Namun faktanya, sebagaimana yang dilansir Kementerian Dalam Negeri (2021), realisasi rata-rata belanja APBD provinsi pada Semester I 2021 hanya sebesar 35,18 persen (Rp138,17 triliun), sementara untuk kabupaten/kota hanya tercapai 33,08 persen (Rp410,06 triliun). Inilah sisi lain ekonomi kita yang sangat rapuh dan inefisien.
Dalam hal realisasi investasi, ketimpangan spasial juga masih sangat mencemaskan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2021) mencatat bahwa selama lima tahun terakhir (2016-2020), realisasi investasi di kawasan timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, dan Maluku-Papua) sangatlah minim ketimbang kawasan barat Indonesia. Sepanjang periode ini, kawasan timur Indonesia hanya mencatat realisasi kumulatif di angka 26,76 persen, jauh dibandingkan dengan Jawa sebesar 53,86 persen, dan tidak terpaut jauh dengan Sumatera di angka 19,36 persen. Bahkan, sepanjang Januari-Desember 2020, jika ketimpangan ini dipandang ekual, yakni realisasi investasi di Jawa sebesar 49,5 persen, kali pertama berada di bawah 50 persen, hal ini karena porsi investasi di Sumatera yang naik menjadi 24,3 persen. Sejatinya, kumulasi investasi di Indonesia Timur stagnan di angka 26,2 persen.
Penulis khawatir, keberhasilan menghindari MIT akan menjadi hal yang delusif belaka, sementara yang nyata adalah masyarakat di sebagian kawasan republik ini masih terjebak di kedalaman rimba dan keterpencilan tengah lautan. Dan pekerjaan merampungkan keterhubungan spasial republik masih butuh waktu dan komitmen kuat. Dengan sendirinya persaingan dalam pasar MEA ini akan semakin berat, serta selain juga semakin kurang relevan dengan komitmen pemerataan. Sementara itu, ketimpangan wilayah dan ruang semakin menganga.
Bahkan, bisa jadi ancaman MIT adalah belaka keriuhan ketimbang perangkap paradigmatiknya. Sebab, sebagaimana ditemukan Robertson dan Ye (2013) dalam kajiannya berjudul “On the Existence of Middle Income Trap,” ide jebakan pendapatan semakin mengarah pada mitos pembangunan. Segala literatur dan bahasan tentangnya berciri informal dan deskriptif semata. Sepertinya republik ini memang suka membangun paradoks. Sekaligus terjebak diksi terminologis.***
Arifuddin Hamid
Tenaga Ahli Anggota Komisi I DPR RI
*Opini dimuat Harian Bisnis Indonesia, 29 Juli 2021 [tanpa suntingan redaksi]