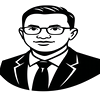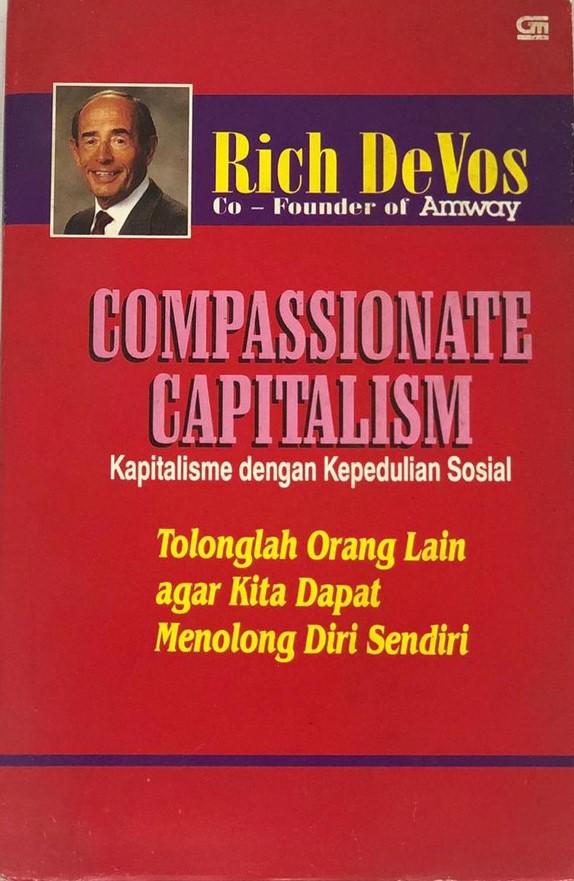Sudah sepantasnya gagasan bernegara, termasuk dalam hal ini ide membangun sistem pemilihan umum mestilah berdasarkan dan menjunjung tinggi hukum sebagaimana digariskan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Karena itu, gagasan pemerintah yang mempertahankan presidential threshold adalah langkah mundur bagi demokrasi dan konstitusionalisme.
Sudah sepantasnya gagasan bernegara, termasuk dalam hal ini ide membangun sistem pemilihan umum mestilah berdasarkan dan menjunjung tinggi hukum sebagaimana digariskan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Karena itu, gagasan pemerintah yang mempertahankan presidential threshold adalah langkah mundur bagi demokrasi dan konstitusionalisme.
Pemerintah sepertinya tidak sadar bahwa gagasan ini sudah usang. Faktanya, presidential threshold tidak memiliki kemampuan membangun koalisi jangka panjang. Kartelisasi politik yang dibangun pemerintah justru mempertaruhkan stabilitas pemerintahan. Langkah pergantian kabinet yang menyisakan implikasi negatif berupa bagi-bagi jatah kekuasaan tentu saja berdampak langsung pada konsistensi kebijakan. Apa yang menjadi kebijakan kementerian sebelumnya bertolak belakang dengan menteri penggantinya.
Bermasalah
Gagasan presidential threshold bermasalah dari aspek hukum dan politik. Dari aspek hukum, klausula ini tidak sejalan dengan penegasan sistem presidensialisme. Dalam sistem presidensialisme, eksistensi lembaga kepresidenan tidak bergantung pada seberapa kuat dukungan parlemen, karena pemerintahan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, begitu pun presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
Ketentuan Pasal 190 RUU Pemilu juga potensial bertentangan dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam Diktum Pendapat Mahkamah halaman 85 Putusan MK tersebut dikatakan bahwa ….”tidak mungkin yang dimaksud “sebelum pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa “sebelum pemilihan umum” dimaknai sebelum Pilpres, maka frasa “sebelum pemilihan umum” tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden.” Apa makna Putusan MK ini?
Ada dua hal yang dapat didiskusikan mendalam. Pertama, MK tidak pernah menjelaskan secara eksplisit frasa “sebelum pemilihan umum” tersebut mengacu pada pemilihan umum yang mana: apakah maksudnya adalah pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Kedua, bahkan jika pun MK mengartikan makna dari frasa tersebut identik dengan Pemilu legislatif, maka menggunakan logika berpikir yang sama dengan pertimbangan MK tersebut, acuan Pemilu legislatif ini pun masih dapat diperdebatkan.
Maka itu, mengartikan Pemilu legislatif adalah Pemilu tahun 2019 masih dapat dibenarkan. Jika tafsirannya seperti ini, makna frasa “sebelum pemilihan umum” tersebut mengacu pada persiapan administratif dan persiapan prapemilulainnya telah cukup mengartikan frasa tersebut. Pelaksanaan pemilu legislatif juga mensyaratkan tahapan tertentu yang pelaksanannya memang sebelum pelaksanaan pemilu legislatif. Sementara Pemilu presiden dan legislatif tahun 2019 dilaksanakan pada waktu bersamaan, maka dengan sendirinya Pemilu presiden tahun 2019 secara otomatis meniadakan syarat ambang batas perolehan suara atau kursi DPR.
Dari sisi politik, keberlakuan klausul ini juga akan sangat mungkin melahirkan krisis legitimasi. Padahal presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 dihasilkan oleh konfigurasi politik pada Pemilu 2014, maka memaksakan hasil Pemilu 2014 sebagai dasar pengajuan calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 sulit menemukan pijakan teoritiknya. Atau pemaksaan terhadap hal ini adalah bentuk dari legitimasi semu yang menegasikan hasil Pemilu tahun 2019.
Padahal, partai politik adalah kolektivisasi ide, hasrat, dan keinginan dari sekelompok orang yang menghimpun diri mengejar struktur kuasa sebagai instrumen perjuangan. Rupa partai ini bersifat determinis, yakni sangat dipengaruhi oleh struktur persepsi dan demografis dalam satuan waktu. Apa yang diinginkan pada tahun 2014 tidak harus selalu sama dengan tahun 2019. Partai politik yang mampu memenangkan hati dan pikiran rakyat pada Pemilu tahun 2014 belum tentu mendapatkan hal yang sama pada tahun 2019.
Di sisi lain, ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungannya. Ketentuan ini menjelaskan keberkaitan antara hasil Pemilu legislatif dengan pencalonan presiden. Calon presiden dilahirkan oleh partai politik atau gabungannya yang memiliki determinasi yang identik, yakni berasal dari basis demografis dan kenyataan sosial yang sama. Karena itu, memaksakan hasil Pemilu 2014 sebagai basis pengajuan calon presiden tahun 2019 adalah wujud dari kesenjangan cara berpikir (contradictio in determinis).
Berbahaya
Apakah demokrasi sedang dalam bahaya? Pertanyaan ini adalah kalimat pembuka buku yang ditulis oleh tiga teoritisi demokrasi (Crozier, Huntington, dan Watanuki, 1975) dalam buku yang juga berjudul dramatis: Demokrasi dalam krisis. Pertanyaan serupa menjadi sangat pantas diajukan atas ide presidential threshold yang tertuang dalam RUU Pemilu. Ketentuan Pasal 190 RUU yang tegas-tegas menyatakan bahwa partai politik atau gabungannya yang berhak mengajukan capres dan cawapres adalah yang perolehan kursinya paling sedikit 20 persen atau suara 25 persen pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya adalah bahasa kuasa yang tidak berpijak di atas prinsip universal demokrasi.
Demokrasi yang sejati menganut prinsip ekualitas, yakni memastikan segala hak dan kedudukan warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Hak memilih dan dipilih adalah hak asasi yang mesti dijamin oleh negara. Karena itu, negara semestinya menjadi garda terdepan dalam memastikan terpenuhi hak konstitusional setiap warga negara ini. Jika sekelompok elite yang mengatasnamakan kehendak negara membajak demokrasi untuk memaksakan kehendak diri dan kelompoknya, maka lonceng kematian demokrasi yang sejati mulai berbunyi.
Dalam konteks inilah gagasan presidential threshold, tidak saja harus dikritisi, namun semua warga negara mesti memperjuangkan alternatif gagasan lain yang lebih demokratis dan konstitusional. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Michael Callahan (2012), if justice is not equal for all, it is not justice. Jika segelintir elit mendaku ide presidential threshold ini adalah bentuk keadilan, maka sudah pasti tidak ada keadilan sama sekali di dalamnya. Keadilan versi elit ini mesti dipandang sebagai gagasan impulsif, kalau tidak lebih tepat disebut berbahaya.***
Arifuddin Hamid
Anggota Salemba Law Community, Alumnus Fakultas Hukum UI
Koran Jakarta, 3 Mei 2017