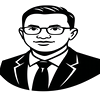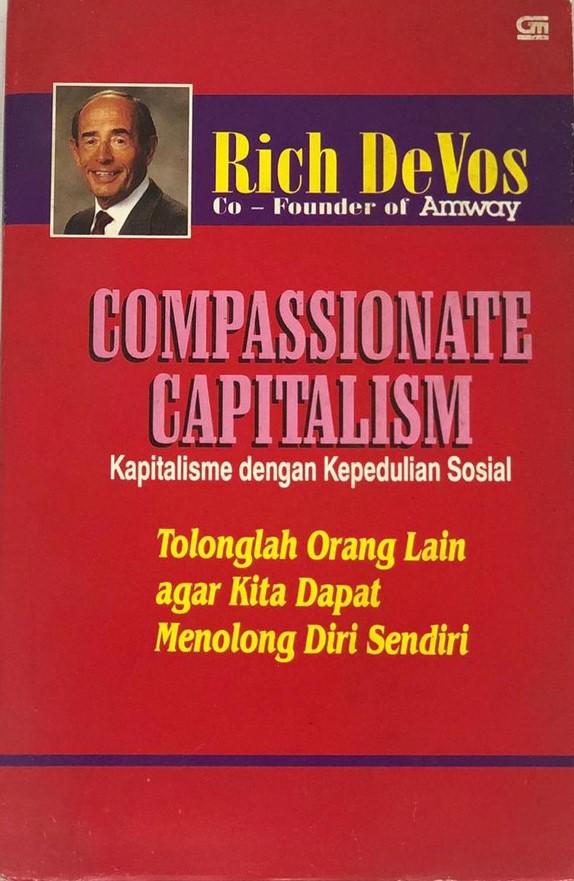Judul: Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992
Judul: Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992
Penulis: Rizal Mallarangeng
Penerjemah: Martin Aleida
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
Cetakan: Ketiga, 2008
Tebal: xl+268 hal.; 14 cm x 21 cm
ISBN: 978-979-9023-71-1
Disertasi Rizal Mallarangeng di Kampus Ohio State University (OSU), Amerika Serikat ini berjudul asli “Liberalizing New Order Indonesia: Ideas, Epistemic Community, and Economic Policy Change, 1986-1992.” Disertasi ini, yang kemudian setelah dialih-bahasakan menjadi sebuah buku berjudul “Mendobrak Sentralisme Ekonomi,” tampaknya berhasrat menjadi warta historis perjalanan ekonomi Indonesia selama kurun waktu 1986-1992. Masa ketika Soeharto kerap digambarkan sedang di puncak hegemoninya, kurun sentralnya peran negara dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negara.
Tidak saja pada bangunan teoritik studinya, gramatikal penulisan yang digunakan oleh Rizal juga terkesan jauh dari angker bahasa yang biasanya ditampilkan suatu karya tertinggi akademik. Dalam alinea-alinea lanjutannya, buku ini tidak saja (sekadar) memotret dinginnya teknis perdebatan ekonomi, namun juga menyoal kompleksitas kebijakan negara, termasuk aktor-aktor terlibat di dalamnya. Buku ini pantas disebut sebagai karya non-mainstream, yang tidak sekadar menjelaskan teorema. Justru sebaliknya sarat dengan variabel nonekonomi. Rizal bahkan tidak saja hendak keluar dari pertarungan operasional, malah lebih jauh memasukkan variabel yang terkesan tidak ekonomistik, tentang pentingnya ide-ide. Tentang peran penting sekelompok orang yang dia sebut dengan komunitas epistemik, lebih tepatnya epistemis liberal.
Mengapa disebut non-mainstream? Karena buku hendak keluar dari belenggu teoritik yang selama ini kadung dipercayai sebagai “kebenaran ilmiah” portofolio kebijakan ekonomi-politik Orde Baru (Orba). Dalam kerangka teoritik yang ditampilkannya, Rizal tampaknya mencoba mengambil perspektif yang lain (the other view). Selama ini, penjelasan atas Orba selalu berpijak pada tiga teori ini: koalisi politik, otonomi negara, dan pilihan rasional (hal. 2-13). Dengan pola pendekatan deskriptif, Rizal menyodorkan suatu asumsi, kalau tidak lebih tepat dikatakan hipotesis, gagasan memainkan peranan penting! Asumsi inilah yang kemudian coba dibuktikan melalui paragraf lanjutan buku ini.
Selain itu dapat dibilang nonekonomi, sebab buku ini berusaha keluar dari pakem metodologi ekonomi kontemporer. Alih-alih mengembangkan kerangka pikir yang instrumentalis dan strukturalis, Rizal lebih jauh mengembangkan pendekatan yang lebih sosiologis. Ciri ini terlihat jelas dalam penggambarannya akan komunitas-komunitas epistemik yang tidak berformat, fleksibel, dan tidak konsisten di antara para pendukungnya. Sumitro dan Sjahrir yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam gagasan kontraliberalisasi justru kemudian berbalik menjadi pendukung utama pandangan tersebut (hal. 137).
Dapat dikata, wacana yang coba dibangun Rizal ini menjadi hal baru, setidaknya ketika buku ini diterbitkan. Selama ini, kalaupun bukan samar-samar, peran kaum epistem ini kerap diyakini sekadar mitos, yang dari waktu ke waktu direproduksi sesuai kondisinya. Bahkan tidak jarang dipolitisir untuk kepentingan politik dan ideologis tertentu. Rizal bahkan menggambarkan Soeharto sebagai aktor dependen yang titik dependensianya sendiri berada pada Soeharto. Bagaikan dalang, Soeharto digambarkan sebagai sosok yang menggelar teater paradoks, dikelilingi oleh berbagai kelompok yang berseberangan.
Dependensi posisi Soeharto ini tergambar dalam pasang surut dominasi kelompok intelektual dalam pertarungan wacana kebijakan selama kurun kekuasaan Orba. Yang menarik, eksistensi kelompok ekonom (teknokrat) menjadi diskursus sentral dalam studi yang dilakukan Rizal ini. Bahkan pembahasan terkait kelompok ini, spesifik simbiosisnya dengan komunitas epistemis liberal dibahas dalam satu bab khusus (hal. 125-158).
Dalam studi ini, pertarungan antarkelompok pemikir terjadi dalam fase dan kurun waktu cukup lama. Rizal membagi fase tersebut ke dalam empat fase, yakni tonggak awal kekuasaan Orba tahun 1967 sampai meletusnya kejadian Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari); pasca-Malari sampai tahun 1985; tahun 1985 sampai tahun 1990; dan terakhir pascatahun 1990. Dalam kurun waktu 1967 sampai meletusnya Malari, kelompok teknokrat berseberangan dengan “kelompok empat,” yang terdiri dari Muhammad Hatta, Soedjatmoko, Sarbini Sumawinata, dan Muchtar Lubis. Selama kurun waktu pasca-Malari sampai dengan tahun 1985, arah kebijakan Indonesia menjadi sentralistik.
Turunnya harga minyak pada medio 1980-an kemudian menjadi stimulan perubahan pendulum, kembalinya eksponen kelompok teknokrat, sekaligus mulai berseminya komunitas epistemis liberal. Selama kurun waktu ini, sampai dengan tahun 1990, dominasi kelompok yang kerap disindir dengan ungkapan “Mafia Berkeley” ini ditandai kebijakan deregulasi ekonomi, privatisasi, dan dibukanya keran perdagangan global dengan maraknya penanaman modal asing. Pendulum kebijakan ini ternyata menemukan resistansinya, yakni oleh kelompok insinyur dan birokrat (kelompok teknolog) yang digawangi oleh Habibie dan Ginandjar Kartasasmita, dengan orientasi kebijakan yang lebih nasionalistik.
Dalam catatan sejarah, periode mulai tahun 1990-an adalah kembalinya pergeseran pendulum, kembali pudarnya dominasi kelompok teknokrat. Periode ini kerap disebut sebagai era “kelelahan deregulasi” (hal. 207). Perlu menjadi catatan penting, Rizal menggambarkan realitas periode ini dengan ungkapan yang dilematis dan berkesan paradoksal. Gencarnya kritikan yang dilontarkan, terutama oleh kelompok teknolog, justru terjadi ketika kondisi perekonomian Indonesia secara statistik menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan mengutip Sadli―salah satu eksponen teknokrat, Rizal menyisir ungkapan yang ramai diperbincangkan kalangan ekonom saat itu: kebijakan deregulasi telah menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Bahkan dengan nada lebih sarkastis, Sadli melontarkan sindiran “good times make bad policies.” Keberhasilan ekonomi membuai Soeharto dan pemerintahnya kembali terjebak sentralisme.
Menolak Lupa
Karya Rizal ini menjadi salah satu studi akademik yang cukup cermat mereportase, sekaligus meruntuhkan mitos bangunan kebijakan strategis Orba yang kerap dianggap “monolitik.” Karya dengan riset menahun ini cukup jeli mendeskripsi lintasan fakta yang sering terlupa, malah dengan pola pembahasan cukup mendetail. Tidak aneh kemudian banyak kalangan mengapresiasi, termasuk William Liddle―Indonesianis terkemuka sekaligus pembimbing disertasinya di OSU―menominasikannya sebagai salah satu penerima penghargaan Departmental Award, salah satu penghargaan intelektual bergengsi di OSU.
Apabila dikontekstualisasi dengan diskursus dan realitas penyusunan kebijakan kekinian (pascareformasi), karya ini penting dijadikan bahan rujukan, sekaligus perbandingan. Dalam era “kembalinya politik,” yakni ditandai oleh desakralisasi kekuasaan dan demokrasi pertisipatoris-proseduralistik, karya yang kemudian berkesan klasik ini penting sebagai penolak lupa. Bahwa pertarungan kebijakan yang pernah terjadi selama kurun kekuasaan Orba tidak saja akademis, malah lebih tepat disebut ideologis.
Seperti ungkapan peribahasa, “Sebuah bangsa dapat dihancurkan, namun tidak dengan gagasan!” Gagasan senantiasa menemukan pengikutnya sendiri, dan itu merupakan proses alamiah yang berjalan-beriring dengan perjalanan waktu. Dan sejarah kembali berulang (?)! Munculnya sekelompok akademisi di “sedalam markas” yang menduduki jabatan strategis di republik ini, yang kerap dianggap sebagai kelanjutan reproduksi kelompok teknokrat berikut kelompok resisten-nya, kasat memperlihatkan berlanjutnya pertarungan ideologis tersebut. Namun pertanyaannya, apakah hal tersebut merupakan―meminjam perspektif Lacanian―adalah the real ‘yang nyata,’ bukanlah suatu reality ‘kenyataan’? Determinisme kebijakan strategis pascareformasi yang menempatkan kekuasaan “tertinggi,” sekaligus “terakhir” sebagaimana normativitas konstitusi 1945 berikut peraturan organiknya oleh “kekuasaan publik” berwujud Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan superfisialitas sekelompok pemikir tersebut? Sehingga pertanyaan lanjutannya, apakah kelompok tersebut benar-benar penting-nyata ada, atau sekadar penampakan dari “yang nyata” dan menjadi penggembira dalam humoritas politik sarat transaksi?
Arifuddin Hamid
Alumnus Fakultas Hukum UI
Jakarta, 21 Juli 2013