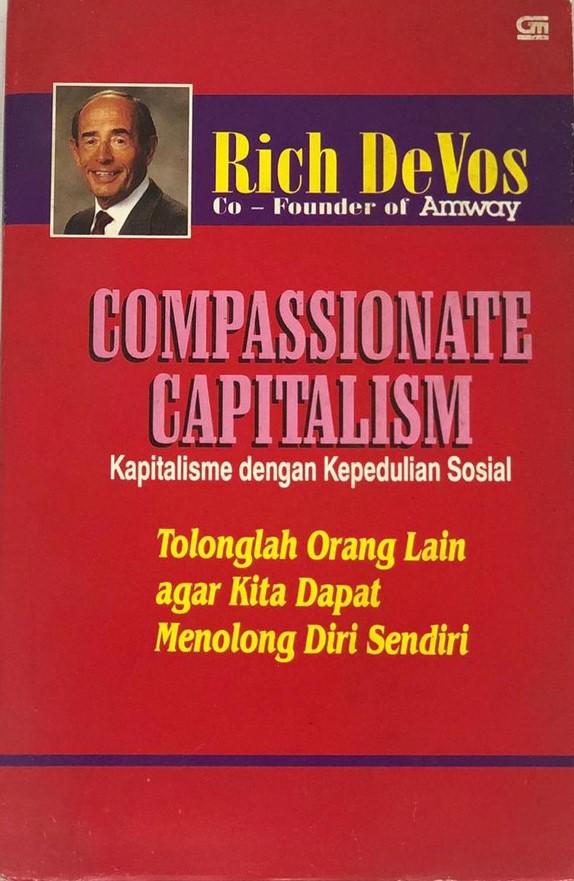Pengesahan RUU APBN Perubahan (APBNP) 2016 melahirkan preseden baru yakni pengurangan target fiskal. Biasanya, APBNP identik dengan penambahan target, terutama target belanja. Karena itu, langkah pemerintah ini patut dipandang sebagai suatu terobosan. Bahwa bagaimana implikasi terobosan ini pada keberlanjutan fiskal, tentu perlu mendapatkan telaah lanjutan.
Pengesahan RUU APBN Perubahan (APBNP) 2016 melahirkan preseden baru yakni pengurangan target fiskal. Biasanya, APBNP identik dengan penambahan target, terutama target belanja. Karena itu, langkah pemerintah ini patut dipandang sebagai suatu terobosan. Bahwa bagaimana implikasi terobosan ini pada keberlanjutan fiskal, tentu perlu mendapatkan telaah lanjutan.
Berisiko
Dalam banyak kesempatan, pemerintah selalu menyatakan bahwa langkah pengurangan target fiskal ini adalah rasionalisasi terbaik menyikapi perkembangan ekonomi global dan domestik. Sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan dan RUU APBNP 2016, melemahnya perekonomian global sepanjang tahun 2015 hingga triwulan pertama 2016 memberi dampak signifikan bagi pelemahan ekonomi domestik. Barangkali sebagian kita akan menyepakati argumentasi ini. Sebagai konsekuensi logis ekonomi kita yang terbuka, maka kondisi eksternal akan berdampak pada situasi di internal negara. Harga minyak di pasaran dunia, misalnya, berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan negara sebab asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dalam APBN 2016 jauh meleset.
Namun persoalannya, apakah kondisi eksternal tersebut adalah rasionalitas utama bagi pengurangan target fiskal ini? Adakalanya kita patut kritis pada klaim yang diajukan pemerintah, bahwa jika memang dasar pengambilan kebijakan ini disebabkan volatilitas global yang memang diluar kendali kita, hal ini wajar saja. Namun ketika ternyata semata disebabkan gagalnya target penerimaan pajak (shortfall), dimensi persoalannya melebar. Ada permasalahan struktural yang tidak kunjung terselesaikan. Sebagai andalan negara paska semakin tertekannya cadangan migas, peran pajak menjadi kian krusial. Rendahnya realisasi penerimaan pajak secara otomatis menghambat berbagai rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Maka itu, revisi kebijakan fiskal sekarang, juga tidak lepas dari pengaruh shortfall pajak.
Dalam UU APBNP 2016, penurunan target penerimaan jauh lebih besar ketimbang target belanja. Jika pada APBN 2016 penerimaan ditetapkan sebesar Rp1.822.545 triilun, pada UU APBNP ditetapkan menurun menjadi Rp1.786.225 triliun (menurun 1,99 persen). Pada target belanja, meskipun mengalami penurunan dari sebelumnya Rp2.095.724 triliun (APBN 2016) menjadi Rp2.082.948 triliun (UU APBNP 2016), penurunnya hanya sebesar 0,6 persen. Fakta ini menjelaskan bahwa defisit akan semakin melebar. Kalau sudah begini, biasanya pemerintah menempuh kebijakan pembiayaan utang guna menutupi defisit tersebut. Jika melihat nalar kebijakan yang memang sudah preferensi defisit pada APBN 2016 lalu, maka pada APBNP ini tekanan defisit akan semakin besar.
Keberlanjutan preseden ini akan berimplikasi langsung pada kian beratnya beban utang. Alasannya sederhana yakni jika fenomena ini menjadi tren, maka pengurangan target penerimaan akan menjadi suatu hal yang biasa. Semua komponen dalam negara akan memakluminya sebagai peristiwa ekonomi belaka, sehingga kebijakan revisi ini adalah langkah yang paling baik. Padahal sejatinya masalah ini bukan sekadar peristiwa ekonomi, namun ekses kegagalan otoritas dalam menghimpun dana pembangunan. Ada tolok ukur yang wajar tentang seberapa layak seseorang warga negara atau korporasi dikenakan pajak. Secara akademik dan praktis, praktik terbaik yang terjadi di berbagai belahan dunia semestinya dijadikan contoh tentang keberhasilan negara memungut pajak tanpa warganya merasa terbebani.
Maka itu, langkah revisi ini adalah terobosan yang berisiko. Pemerintah tidak saja mempertaruhkan iklim investasi dan bisnis yang potensial melahirkan sentimen negatif pelaku usaha, lebih dari itu, memaklumi kegagalan kinerja otoritas pajak. Menjadi lebih dilematis ketika program reformasi pajak hanya berhenti pada skema insentif pajak bagi sektor swasta, namun abai terhadap reformasi struktural dalam menata kinerja institusi perpajakan sendiri. Dari berbagai komitmen ambisius pemerintah, sangat jarang kita mendengar langkah nyata pemerintah dalam memperbaiki sengkarut kelembagaan ini. Padahal sudah banyak analisis, masukan, bahkan kritik dari berbagai pihak tentang persoalan utama perpajakan. Pada intinya, jangkar masalahnya terletak pada inefektivitas kelembagaan.
Ketika pemerintah hanya berfokus pada agenda jangka pendek seperti pengampunan pajak namun selalu saja abai pada target jangka panjang, maka preseden ini rawan menjadi siklus tahunan. Bahwa meskipun pengampunan pajak akan langsung mengerek dana pembangunan, secara empirik, setiap kebijakan aji mumpung hanya melahirkan ekses destruktif bagi kebijakan yang berkelanjutan. Apalagi sudah banyak pihak yang, tidak saja menyatakan kebijakan ini berpotensi melanggar hukum, namun mulai meragukan efektivitas pelaksanaannya. Argumennya sederhana, bahkan terkesan klasik: administrasi perpajakan masih rapuh.
Maksud hati menempuh langkah kontroversial berupa pengampunan pajak, pemerintah malah dihadapkan pada kegagalan tradisionalnya. Pemerintah sedang dilanda paradoks berganda. Kebijakan jalan pintas untuk menutupi shortfall pajak ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pada kelembagaan yang buruk, kebijakan ini hanya melahirkan ekses derivatif yang merusak, yakni ketebelece penegakan hukum dan kegagalan penerimaan sekaligus. Paradoks ini hanya akan membuat republik makin terpuruk, ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kebijakan insentif pajak ini adalah pertaruhan besar yang tidak hanya meruntuhkan agenda besar penegakan hukum, tetapi menjadi sinyal tidak seriusnya pemerintah dalam menata tata pemerintahan (governance). Tidak mengherankan jika publik dan pelaku usaha akan memandang komitmen reformasi birokrasi, atau bahkan revolusi mental, sebagai jargonistik belaka.
Karena itu, dengan deklarasi kemerosotan fiskal ini, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya keras untuk merasionalkan kebijakan teknis yang diambilnya. Satu hal yang merupakan determinasi (faktorial kebergantungan) adalah peringkat investasi (investment grade) Indonesia yang masih mengalami stagnasi panjang. Lembaga pemeringkat Standard&Poor’s tentu tidak perlu melakukan klarifikasi panjang atas kualitas penilaiannya dengan adanya kenyataan fiskal ini. Upaya penyangkalan bahkan sorotan taklid atas hasil riset lembaga tersebut oleh pejabat pemerintah akan sia-sia belaka. Maka langkah paling bijak, perlu, dan mendesak adalah memperbaiki kualitas kelembagaan dan basis penyusunan kebijakan. Kedua hal yang telah menjadi penyakit endemik ini memerlukan terobosan jitu yang lebih tepat dan lebih minim risiko.
Arifuddin Hamid
Mahasiswa Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
Dimuat Suara NTB, 26 Juli 2016.