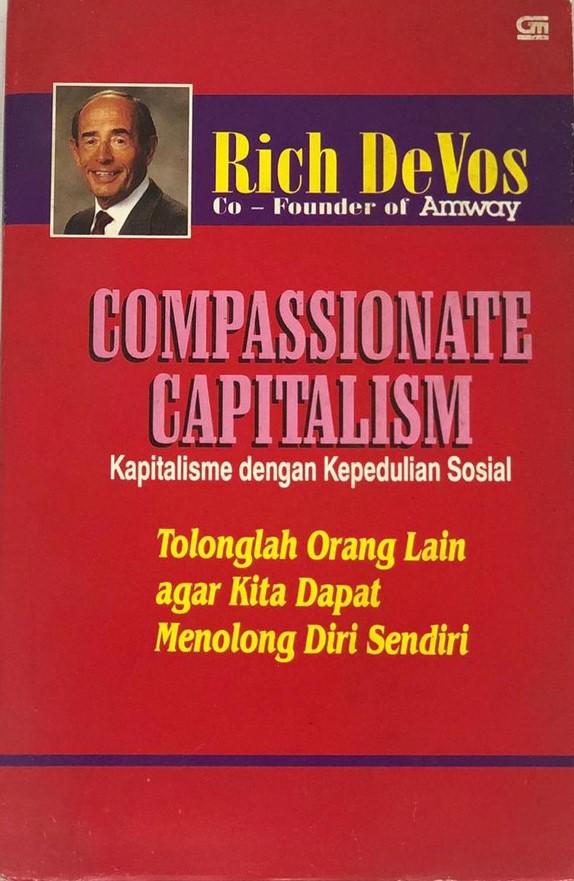Komitmen pemerataan pembangunan betul-betul diwujudkan pemerintah melalui penetapan APBN-P 2016 yang alokasi dana daerah (dana perimbangan, DAK/penyesuaian, dan dana desa) telah melampaui alokasi kementerian/lembaga (K/L). Bagi sebagian pihak, struktur belanja progresif ini meniscayakan produktivitas daerah dan keberhasilan pembangunannya. Tetapi sebelum kita terpapar optimisme dan ujungnya terjerumus delusi, ada baiknya membedah faktorial prasyarat dan lalu bertanya, sejauh mana keniscayaan itu tersedia?
Komitmen pemerataan pembangunan betul-betul diwujudkan pemerintah melalui penetapan APBN-P 2016 yang alokasi dana daerah (dana perimbangan, DAK/penyesuaian, dan dana desa) telah melampaui alokasi kementerian/lembaga (K/L). Bagi sebagian pihak, struktur belanja progresif ini meniscayakan produktivitas daerah dan keberhasilan pembangunannya. Tetapi sebelum kita terpapar optimisme dan ujungnya terjerumus delusi, ada baiknya membedah faktorial prasyarat dan lalu bertanya, sejauh mana keniscayaan itu tersedia?
Selama dasawarsa terakhir, alokasi kumulatif dana daerah menanjak signifikan dan simultan. Pada tahun 2007, dana daerah dialokasikan sebesar Rp254,2 triliun, terus menaik hingga mencapai angka Rp770,17 triliun pada APBN 2016. Rasio dana daerah dengan total belanja juga relatif menaik drastis sejak masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Pada tahun 2014, rasionya sebesar 31,78 persen, kemudian terus menaik lebih besar ketimbang rasio-rasio tahun sebelumnya, yakni 33,49 persen pada tahun 2015 dan 36,75 persen pada 2016 ini. Dari skala rasio ini terlihat bahwa komitmen desentralisasi fiskal pemerintah terwujudkan secara nyata.
Dari sisi laju pertumbuhan, secara umum pendanaan dana daerah tumbuh lebih signifikan ketimbang pertumbuhan total dana belanja. Bahkan pertumbuhan ini relatif bergerak konsisten di atas 10 persen per tahun dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 13,36 persen, kecuali tahun 2009 yang sempat mengalami kontraksi (tumbuh hanya 5,78 persen). Di masa depan, jika pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan membangun negara dari pinggiran, dapat dipastikan alokasi dana daerah akan semakin membesar. Fakta inilah yang pada ujungnya membuat publik perlu bertanya, sejauh mana daya ungkit desentralisasi fiskal ini pada pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Determinasi
Menguji produktif atau tidaknya desentralisasi fiskal ini perlu berpijak pada sejauh mana dana tersebut digunakan untuk menopang produktivitas daerah, atau sebaliknya fakta determinasi apa yang membuat penggunaan dana ini tidak optimal. Ini berarti, terlepas dari beban teoritiknya, penggunaan dana ini untuk alokasi sektor-sektor yang dianggap perlu oleh pemerintah mestinya memiliki produktivitas yang tinggi. Katakanlah misalnya masih dominannya alokasi APBD untuk belanja pegawai pada sejumlah daerah, kebijakan ini mestinya memiliki dampak positif bagi produktivitas daerah bersangkutan. Bahwa meskipun kebijakan ini patut dievaluasi sebab dianggap rendah daya ungkitnya, bahkan menghambat produktivitas, setidaknya pemerintah daerah harus dapat menjamin laju pertumbuhan kinerja aparatur bergerak meningkat dari tahun ke tahun.
Sebab sejatinya aparatur berkualitas memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian daerah. Dengan membaiknya pelayanan publik, kondusivitas iklim usaha dapat terjaga dengan baik. Hal yang sama juga berlaku untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada aspek pelayanan kesehatan dan pendidikan bangku sekolah. Kombinasi ideal berbagai faktor tersebut pada akhirnya menciptakan pembangunan lebih berkualitas. Oleh karenanya disain kelembagaan ini mestinya determinan pada faktorial efisiensi, yakni relasi kausalitas antara jumlah aparatur dengan beban kinerja birokrasi.
Masalah muncul ketika daerah tidak memiliki standar produktivitas kelembagaan yang rasional dan terukur. Tingginya beban fiskal untuk belanja pegawai dan membengkaknya jumlah aparatur birokrasi adalah variabel penjelas mengapa selama ini pembangunan birokrasi kita tidak pernah mampu mendorong kemajuan daerah. Sementara di sisi lain, kebijakan reformasi birokrasi yang bertumpu pada perbaikan kinerja aparatur juga belum menunjukkan hasil optimal, padahal kebijakan ini sudah diimplementasikan selama bertahun-tahun. Karena inefisiensi ini, tidak aneh kemudian sejumlah pihak menyarankan privatisasi birokrasi. Agenda penggunaan sektor swasta dalam penyediaan barang dan jasa yang meliputi pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan kualitas (Kosar, 2006) ini diharapkan akan mendorong efisiensi, memperbesar simpanan fiskal, meningkatnya pengawasan dalam sistem administrasi negara, dan memperoleh dividen politik (Michaels, 2013).
Di sisi lain, meskipun alokasi dana daerah untuk pembangunan infrastruktur naik signifikan dari tahun ke tahun, kualitas infrastruktur di daerah juga tidak menunjukkan hasil yang optimal. Pada tahun 2016 ini, total DAK fisik mencapai Rp85,5 triliun, naik signifikan dibandingkan total DAK tahun lalu yang hanya senilai Rp58,8 triliun. Akan tetapi kenaikan alokasi ini justru menjadi ladang korupsi. Kalau dulu korupsi pembangunan jalan bermodus pengurangan kuantitas materialnya (Olken, 2004), tidak tertutup kemungkinan akan muncul modus baru yang lebih canggih dan berskala masif. Karenanya tidaklah mengherankan jika daya saing infrastruktur jalan kita masih sangat rendah, yakni hanya menempati peringkat ke-80 dari 140 negara, kalah jauh ketimbang Malaysia dan Thailand yang berperingkat 15 dan 51 (World Economic Forum, 2015).
Kebijakan genjot infrastruktur ini juga berwajah multi paradoks. Desentralisasi yang bertumpu pada pembangunan masif infrastruktur fisik ternyata belum mampu meningkatkan kinerja perekonomian. Bahkan secara histroris, dalam studi Pepinsky dan Wihardja (2011) yang mencoba melihat relasi kausal desentralisasi dengan kinerja ekonomi tercatat bahwa selama kurun 2001-2007, tidak ada bukti valid untuk menunjukkan dampak desentralisasi pada pembangunan Indonesia. Karena itu studi ini menyarankan kepada pemerintah untuk lebih cermat dalam mendisain kebijakan intervensi skala besar seperti desentralisasi. Hambatan desentralisasi ini ternyata tidak berhenti di wilayah ekonomi dan konstruksi. Ironi kembali muncul ketika persepsi regulasi antarpemerintahan mengalami strukturasi asimetrik.
Pada akhir 2015 lalu kita dikejutkan dengan membengkaknya dana simpanan pemerintah daerah di sejumlah bank pemerintah. Di triwulan pertama 2016, kita patut khawatir dengan realisasi penganggaran daerah yang sangat rendah. Sementara kepala daerah kerap berapologi represifnya penegakan hukum pidana sehingga menyebar ranjau ketakutan untuk inovasi kerja-kerja pembangunan. Di sisi lain, pemerintah pusat hanya mampu menawarkan jalan asistensi untuk mengurai sengkarut yuridis tersebut. Maka rendahnya kinerja pembangunan di triwulan pertama 2016 adalah realitas jamak dan konsekuensi logis belaka. Semua kerumitan desentralisasi ini pada ujungnya meniscayakan kesigapan pemerintah dalam mencari jalan keluar atas kedua faktorial determinasi itu. Sebab jika kelembagaan yang buruk dan persilangan legalistik ini tidak disikapi dengan tepat arah, segala komitmen membangun Indonesia dari pinggiran yang bertumpu pada pembangunan infrastruktur hanya akan terlihat pada membengkaknya dana desentralisasi, namun defisit produktivitas.
Arifuddin Hamid
Mahasiswa Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
Dimuat Suara NTB, 2 Agustus 2016