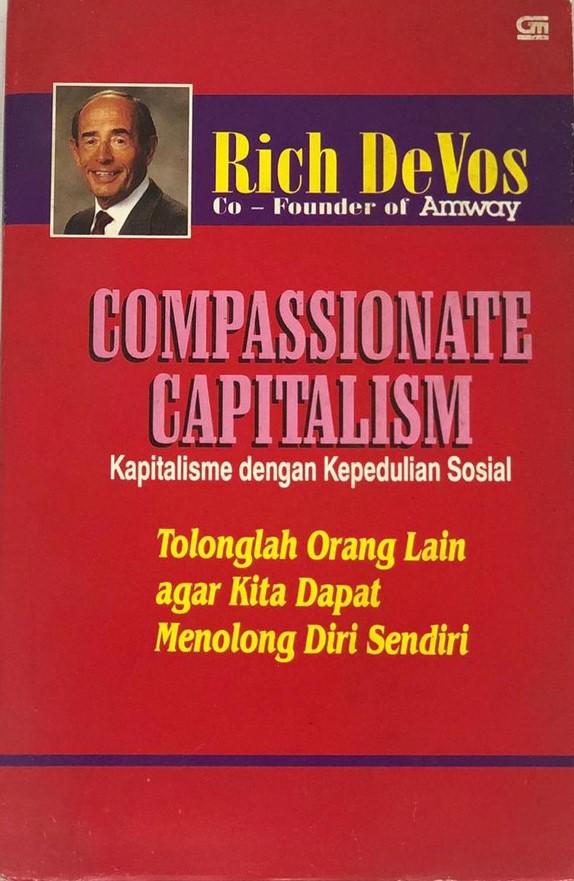Bahwa normatif UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan klausula kewajiban divestasi berkesan nasionalistik, masih tetap menyisa celah praksis yang, tidak saja artifisial, namun juga kontraproduktif. Ini semua berawal dari rumusan normatif yang menyatakan definistik peserta Indonesia adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional (Pasal 112 ayat 1 UU Minerba). Klausula divestasi ini, yang terakhir diatur lebih lanjut dalam PP No. 24/2012, tampaknya tidak berusaha menjawab persoalan tersebut, kalau tidak tepat dikatakan mempertajam persoalan.
Bahwa normatif UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan klausula kewajiban divestasi berkesan nasionalistik, masih tetap menyisa celah praksis yang, tidak saja artifisial, namun juga kontraproduktif. Ini semua berawal dari rumusan normatif yang menyatakan definistik peserta Indonesia adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional (Pasal 112 ayat 1 UU Minerba). Klausula divestasi ini, yang terakhir diatur lebih lanjut dalam PP No. 24/2012, tampaknya tidak berusaha menjawab persoalan tersebut, kalau tidak tepat dikatakan mempertajam persoalan.
Landskap legalistik tersebut menjadikan pertanyaan-pertanyaan berikut menjadi relevan untuk diajukan. Mengapa penerapan UU Minerba terkesan parsial dan menunjukkan ketidaksigapan pemerintah? Apa artinya praksis usaha patungan PT. Daerah Maju Bersaing (PT. DMB) dan PT. Multi Capital (PT. MC) dalam pembentukan PT. Multi Daerah Bersaing (PT. MDB) sebagai salah satu pemegang saham PT. Newmont Nusa Tenggara (Newmont)? Dan relevansi yuridik apa yang menjadikan perdebatan divestasi menjadi demikian alot?
Celah Praksis
Artifisialitas normatif UU Minerba dengan segenap peraturan organiknya adalah ekses logis dari jargon nasionalistik yang kerap ternisbatkan. Bahwa seakan “keadilan yang berkesejahteraan” akan tercapai tatkala merkantilisme regulatif ini dilembagakan dalam suatu paket kebijakan. Jargonistik ini berpotensi gagal menjelma menjadi suatu pengaturan berkeadilan disebab mengalami kekeliruan konsepsional sedari awal. Kekeliruan tersebut, yang juga secara serampangan diracik dalam satu-kesatuan dan kesejajaran posisional badan usaha oleh UU Minerba, semakin menubuatkan kekaburan proyektif. Terlebih klausula ini gagal menemukan diktum teoritik kesejajaran badan usaha berbasis “negara” dengan badan usaha swasta yang semata berorientasi profit.
Dalam aras yang lebih administratif, normativitas produk hukum tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar ketidaksengajaan teknis. Menjadikan berjarak antara apa yang “proseduralistik” dengan sesuatu yang “substantif” adalah bentuk kekeliruan yang lain. Persis inilah simpulan awal yang disadari penulis dalam klausula Pasal 112 termaksud. Doktrin universal dalam ilmu hukum yang mengklasifikasi peran pemerintah ke dalam peran publik dan privat bukanlah proposisi nondeterministik. Peran tersebut terjaga oleh tujuan daripada keterlibatan negara, yakni sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945 guna pemajuan kesejahteraan umum. Penjelmaan negara dalam format BUMN/BUMD bukanlah untuk usaha itu sendiri, melainkan semata instrumen dalam rangka menjamin kesejahteraan―penopangan penerimaan negara/daerah. Oleh karenanya, penulis tidak hendak membaca klausula UU Minerba ini sebagai belaka klausula sepele. Klausula ini, apabila kemudian tidak dijadikan wacana publik, menyimpan celah apologis yang tidak sepele.
Kategorisasi sembrono aktor usaha yang terjejak dalam UU Minerba ini berimplikasi pada level proses dan keluaran usaha patungan Pemda dan swasta nasional terkait kepemilikan saham Newmont. Pada level proses, komposisi kepemilikan saham yang timpang antara PT. MC yang menguasai saham sebesar 75 persen dan PT. DMB sebesar 25 persen dari 24 persen total saham milik PT. MDB di Newmont adalah penjelas awal ketidakberesan berikutnya. Portofolio keuangan Pemda di NTB yang sebagian besar dipasok dari dana transfer adalah bara persoalan yang selalu saja malas untuk dilirik. Padahal salah satu indikator yang menunjukkan kinerja keuangan daerah adalah rasio kemandiriannya, yakni untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (Halim, 2002).
Mencermati postur fiskal di tiga Pemda tersebut, kondisinya tidak dapat dikatakan sehat. Tren kenaikan simultan pendapatan daerah adalah realitas superfisial belaka. Bahwa tren proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2010-2013) relatif mengalami kenaikan, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tetap berada pada kisaran yang sangat kecil. Pada Pemda NTB, kontribusi PAD secara rerata berada pada angka 37,28 persen. Fakta lebih miris justru terjadi di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Di Sumbawa, rerata kontribusi PAD hanya mampu berada pada angka 7,68 persen, sementara Sumbawa Barat hanya mampu berkontribusi di kisaran 12,36 persen. Tren kenaikan tersebut menjadi tidak berarti ketika menilik tren pertumbuhan PAD, bahkan pada Pemda Sumbawa Barat terjadi pertumbuhan PAD yang negatif.
Pada level keluaran (bagi keuntungan), terjadi persoalan ganda: komitmen dan realitas. Menyoal komitmen, kesepakatan kerjasama antara pihak Pemda dengan swasta nasional memang telah bermasalah sedari konsep. Adanya klausula penyerahan selisih jumlah kelebihan dividen kepada pihak kedua (PT. MC) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (12) huruf b nota kesepahaman, menjadi apologi legal yang rawan dipelintir. Kelemahan konsep tersebut juga tercermin pada ketidakjelasan sumber dana pihak kedua sebagai dana talangan bersama membentuk suatu perusahaan baru (PT. MDB).
Celah yuridik tersebut memang ternyata terbukti dalam realitas pembagian dividen Newmont. Berdasarkan laporan keuangan PT. Bumi Resources Mineral Tbk (induk PT. MC) kuartal 1 tahun 2013, jatuh tempo pembayaran utang PT. MDB kepada Credit Suisse AG, Singapura jatuh pada tanggal 18 September 2013. Utang untuk kebutuhan modal kerja sebesar US$316,176,412, suatu angka yang terbilang besar. Lantas bagaimana kedudukan hukum PT. DMB? Apabila mencermati klausula perjanjian antara PT. MDB dan Credit Suisse AG, jaminan atas kredit utang tersebut adalah kepemilikan saham PT. MDB di Newmont, termasuk kuasa untuk menjual saham kepada kreditor. Klausula tersebut berimplikasi pada hilangnya saham Pemda sebesar 6%, yang membuat Pemda rugi dua kali, yakni tidak mendapatkan dividen yang semestinya dan kehilangan hak untuk mendapat dividen dalam pembagian keuntungan Newmont berikutnya.
Sengkarut divestasi juga masih berepisode lanjut, yakni terkait posisi tawar keperansertaan Indonesia. Klausula wajib memiliki minimal 51% saham adalah Parsialistik belaka. Faktanya, hampir semua perusahaan besar yang menguasai mineral strategis di republik ini sebagian besar sahamnya berkepemilikan asing. Lalu apakah dengan skenario saham divestasi 7% tersebut dimiliki pemerintah, persis manajemen Newmont berkehendak negara (state driven)? Kepenguasaan saham oleh Nusa Tenggara Partnership―konsorsium Newmont Mining dan Sumitomo―saat ini adalah 56%, yang artinya dengan pelepasan saham 7% tersebut masih dominan dengan saham sebesar 49%. Sementara secara aktual, dengan skenario bagaimanapun, negara tetap tidak bersaham mayoritas. Bukankah pengambilan keputusan dalam forum tertinggi suatu perusahaan adalah satu saham satu suara (one share one vote)? Dalam konstruksi normatif UU. No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, penentu strategis tetap berada di tangan Nusa Tenggara Partnership (Pasal 84 ayat 1).
Atau barangkali untuk pertanyaan lanjutan, apa jaminan bahwa dalam forum pengambilan keputusan, peserta Indonesia kemudian sama-sepakat atas suatu kebijakan? Bukankah nalar utama perusahaan swasta adalah mencari keuntungan? Apalagi itu, bahkan BUMN dan BUMD juga dibentuk sebagai penopang penerimaan negara, yang nalarnya melulu ekonomistik. Perusahaan perseroan bukanlah perusahaan umum, yang sebaliknya semata berorientasi pelayanan publik.
Preseden Yuridik
Pangkal pokok divestasi sejatinya bukan terletak pada kejadian hukum sebagaimana realitas sengkarut berlarut divestasi saham Newmont. Lebih jauh ini menyasar suatu preseden yuridik, kejadian hukum tersebut merupakan cuilan dari semesta potensi peristiwa hukum. Epos nasionalistik yang kerap dinisbatkan pada normatif UU Minerba ternyata menyimpan borok legalistik, yang rawan dipelintir beratas nama. Padahal Bung Hatta telah berkali menubuatkan bahwa rakyat bukanlah konsep ekonomi, bukan pula hukum, melainkan konsep politik belaka. Dia diskursif semata, bukanlah proposisi deterministik yang dapat dikuantifikasi. Tafsir ‘untuk rakyat’ yang belakangan berjargon nasionalisme ekonomi tampaknya membuat semuanya serba parsial.
Kejadian hukum tersebut memang belum menyesaki lokus republik dan belum menjelma menjadi peristiwa hukum. Tapi kalau kecelakaan yuridis ini tidak dikaji menjadi suatu determinasi legalisme, bukankah potensi penyesakan tersebut besar adanya? Pertanyan-pertanyaan inilah yang menyiratkan bahwa kemerdekaan kita sekadar delusi―keyakinan tidak berdasar. Bahwa hukum organik di republik ini belum merdeka sejak dari pikiran!
Arifuddin Hamid
Warga NTB, Alumnus Fakultas Hukum UI
*Opini dimuat Suara NTB, 5/9/2013