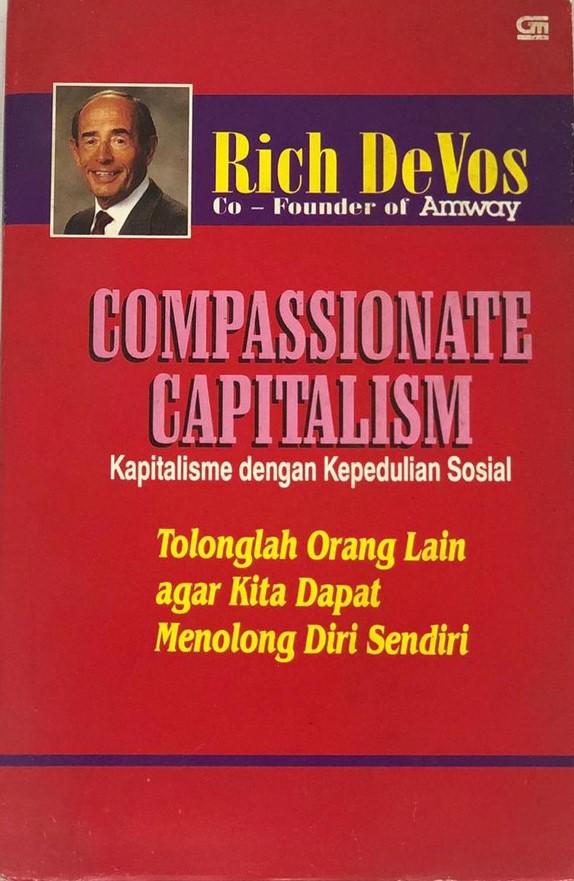Lagi-lagi dan selalu begitu, kawasan timur Indonesia tidak pernah bangun dari ritus kelam ketertinggalan pembangunan. Pembangunan di wilayah ini masih terjebak stagnasi panjang dan urung mengejar gempita pertumbuhan ekonomi yang sedang dinikmati wilayah lain di republik ini. Topik terkait kawasan ini selalu saja bernada pesimistik, kelabu, dan tidak atraktif. Karena itu tidaklah mengherankan jika wacana dan kebijakan pembangunannya kerap diselipi terminologi afirmasi. Secara semantik, terminologi ini menjelaskan ketidakberdayaan dan dependensi endemik. Dari 122 daerah tertinggal yang ditetapkan dalam Perpres 131/2015, 103 kabupaten (84 persen) di antaranya termasuk dalam kawasan timur Indonesia. Kualifikasi ini didasarkan pada faktorial kombinasi, yakni kondisi perekonomian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, kapasitas fiskal, dan karakteristik geografis. Oleh sebab itu, kesiapan kawasan ini dalam menghadapi realisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah mulai berlaku efektif sangatlah mencemaskan.
Lagi-lagi dan selalu begitu, kawasan timur Indonesia tidak pernah bangun dari ritus kelam ketertinggalan pembangunan. Pembangunan di wilayah ini masih terjebak stagnasi panjang dan urung mengejar gempita pertumbuhan ekonomi yang sedang dinikmati wilayah lain di republik ini. Topik terkait kawasan ini selalu saja bernada pesimistik, kelabu, dan tidak atraktif. Karena itu tidaklah mengherankan jika wacana dan kebijakan pembangunannya kerap diselipi terminologi afirmasi. Secara semantik, terminologi ini menjelaskan ketidakberdayaan dan dependensi endemik. Dari 122 daerah tertinggal yang ditetapkan dalam Perpres 131/2015, 103 kabupaten (84 persen) di antaranya termasuk dalam kawasan timur Indonesia. Kualifikasi ini didasarkan pada faktorial kombinasi, yakni kondisi perekonomian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, kapasitas fiskal, dan karakteristik geografis. Oleh sebab itu, kesiapan kawasan ini dalam menghadapi realisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah mulai berlaku efektif sangatlah mencemaskan.
Pasalnya, sebagai wujud aktual liberalisasi perdagangan, MEA akan menawarkan formula yang sama dengan skema perdagangan bebas lainnya: kompetisi. Secara teoritik, kompetisi membutuhkan daya saing dan daya saing lahir dari produktivitas yang tinggi. Membangun produktivitas adalah melalui peningkatan kapasitas faktor produksi, yang terdiri dari modal fisik, manusia, dan penguasaan teknologi. Siklus ini adalah keniscayaan baku dalam era persaingan terbuka dan telah dimaklumi sebagai postulat global. Oleh karenanya, tanpa kesiapan faktor produksi ini, pembangunan berkemakmuran hanya menjadi sebatas imaji, kalau tidak lebih tepat disebut delusi. Delusi ini bukanlah belaka fakta ikonik, sebab kenyataannya berbagai variabel penjelas bagi pengungkitan ekonomi mengalami degradasi yang akut.
Karena kondisi demikian, pemerintah sampai merasa perlu mempertegas kebijakan afirmasi pembangunan kawasan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2000 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Struktur keanggotan dewan ini sangatlah kuat sehingga presiden dan wakil presiden bahkan berlaku sebagai ketua dan wakil ketua, serta beranggotakan 17 kementerian. Alasan di balik kebijakan afirmasi ini tentu mudah ditebak, yakni ketertinggalan kawasan ini di hampir segala bidang memerlukan penanganan yang menyeluruh dan sistemik. Tidaklah mengherankan pula jika pemerintah mewujudkan secara nyata komitmen ini melalui penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet) yang telah mengalami berkali-kali revisi, ditetapkan dari masa Presiden Soeharto sampai Pemerintahan SBY. Dari 14 Kapet yang ada, 12 di antaranya terletak di kawasan timur Indonesia. Namun lagi-lagi, upaya pemajuan kawasan ini tidaklah mudah dan harus melalui jalan belukar, sehingga Presiden Joko Widodo memutuskan pembubaran institusi dan paket kebijakan afirmasi ini.
Upaya Bersama
Membangun kawasan ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada negara. Persoalan struktural yang dihadapi wilayah ini adalah kombinasi akumulatif berbagai faktorial penghambat pembangunan. Kawasan ini mengalami kendala konektivitas sebab biaya pembangunan infrastruktur fisiknya membutuhkan biaya yang sangat besar. Lanskap keruangannya yang dilingkupi perairan luas, pulau yang berjarak, serta kondisi geologis yang sulit tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh negara yang kapasitas fiskalnya terbatas. Tidak aneh jika pergerakan barang dan jasa, serta pertukaran informasi dan alih keterampilan antarkawasan tidak berlangsung dengan optimal. Karena itu perlu langkah inovatif untuk memicu keterlibatan pihak selain negara untuk proaktif menggerakan roda perekonomian di wilayah ini.
Kawasan ini sebenarnya memiliki potensi komersil. Di industri migas misalnya, banyak pihak yang meyakini kawasan ini sebagai penyangga masa depan ketahanan energi domestik. Gas alam di Blok Masela, Provinsi Maluku yang kerap disebut lapangan gas abadi sejatinya membuktikan pengakuan publik atas potensi alam yang dimilikinya. Namun lagi-lagi, pemanfaatan kekayaan energi ini membutuhkan dana yang sangat besar dan investasi jangka panjang yang beresiko tinggi. Potret ini menjelaskan peta parsial potensi ekonomi sekaligus tantangan bagi pengelolaannya. Untuk biaya eksplorasi migas di laut dalam ini, setidaknya harus menyediakan dana sebesar 100-200 juta USD dengan skala keberhasilan 25 persen saja (Olsson, 2015) Dengan demikian, biaya eksplorasi gas di Blok Masela setidaknya senilai Rp2,66 triliun, yang pelaksanaan eksplorasi ini pun belum tentu berhasil.
Sejalan dengan ekonomi biaya tinggi yang telah bersifat alamiah, arus investasi di wilayah ini cenderung mengalami stagnasi. Dalam hal arus investasi asing langsung, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2016) mencatat bahwa selama 5 tahun terakhir (2010-2015), realisasi investasi di kawasan ini sangatlah minim ketimbang kawasan barat Indonesia. Bandingkan dengan Jawa, misalnya, yang selama periode tersebut, realisasi investasi asing di 4 provinsinya rata-rata mencapai 57,98 persen dari total investasi asing di seluruh Indonesia. Dalam laporan ini juga tercatat ada 2 provinsi di kawasan timur Indonesia yang kinerja investasinya berpredikat buruk, yakni Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Untuk Kalimantan Utara, rendahnya kinerja investasi disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas primer yang menjadi andalan kawasan ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah kondisi investasi di Maluku Utara.
Selain karena faktor pembiayaan, persoalan ini ternyata disebabkan oleh rendahnya ketersediaan sumber daya manusia berkualitas. Fakta tersebut menggambarkan bahwa upaya pembangunan ekonomi kawasan harus menempuh lajur yang terjal dan berliku. Dan oleh sebab itu, reformasi struktural, utamanya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam data rilisan Badan Pusat Statistik (2016), indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah timur Indonesia di tahun 2015 masih sangat tertinggal dibandingkan dengan capaian IPM di wilayah Jawa dan Sumatera. Jika menarik batas demarkasi wilayah ini mencakup Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Kepulauan Maluku dan Papua, maka hanya ada empat provinsi yang mencatat hasil IPM yang memuaskan: Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.
Maka itu, langkah mengurangi kendala struktural ini mesti melibatkan masyarakat sipil dan swasta korporasi. Sulit mengharapkan negara mampu berbuat banyak di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan perekonomian yang mengharuskan pilihan kebijakan bersandar pada target keekonomian jangka pendek. Pembangunan kemanusiaan adalah kerja jangka panjang yang hasilnya juga baru akan terasa setelah sekian puluh tahun. Selain itu, investasi modal manusia ini bukanlah seperti investasi fisik yang ketika dibangun langsung dapat dioptimalisasi penggunaannya. Membangun manusia adalah membangun peradaban itu sendiri, dan pembangunannya melekat dalam proses kehidupan publik yang berlangsung. Di titik ini pulalah dukungan swasta korporasi menjadi sangat krusial yakni melalui penggunaan sebagian laba perusahaan bagi pengembangan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Jika kerjasama ini dapat berjalan baik, maka lambat laun disparitas pembangunan yang kerap dituding telah bersifat endemik, dapat diakhiri. Atau setidaknya dapat dikurangi dengan signifikan dan nyata hasilnya.***
Arifuddin Hamid
Mahasiswa Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
Opini dimuat Harian Suara NTB, 13 Juli 2016