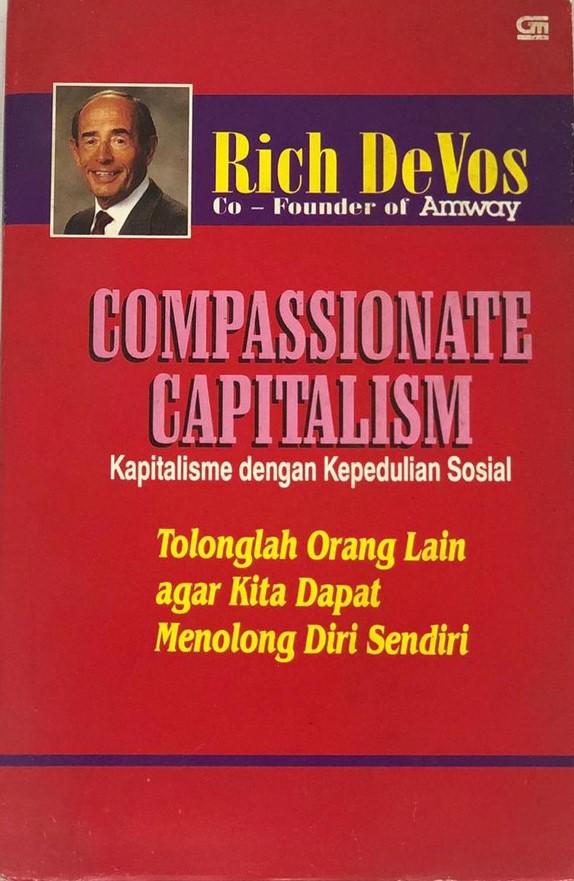Wacana pengampunan pajak (tax amnesty) yang melulu dianggap sebagai postulat kunci mengurangi defisit fiskal sepertinya semakin laik dan perlu untuk ditinjau ulang. Sebab faktanya, realisasi anggaran pada triwulan pertama tahun 2016 ini hanya mampu menyentuh angka 8 persen untuk provinsi dan 8,3 persen untuk kabupaten/kota. Fakta ini rupanya menjelaskan sisi lain kinerja anggaran kita yang tidak berkualitas. Serapan anggaran yang rendah ini berimplikasi pada beban utang yang saban hari kian menunjukkan jumlah yang menaik. Karena itu, tidak mengherankan jika sebagian pihak menyatakan bahwa persoalan anggaran kita bukanlah semata pada kurangnya sisi penerimaan negara, melainkan pada rendahnya kualitas belanja. Fakta ini pula yang menjelaskan neraca APBN kita sepertinya inkongruen dan asimetris. Pada akhirnya, menjadi suatu kewajaran jika wacana pengampunan pajak mendapat resistensi yang meluas.
Wacana pengampunan pajak (tax amnesty) yang melulu dianggap sebagai postulat kunci mengurangi defisit fiskal sepertinya semakin laik dan perlu untuk ditinjau ulang. Sebab faktanya, realisasi anggaran pada triwulan pertama tahun 2016 ini hanya mampu menyentuh angka 8 persen untuk provinsi dan 8,3 persen untuk kabupaten/kota. Fakta ini rupanya menjelaskan sisi lain kinerja anggaran kita yang tidak berkualitas. Serapan anggaran yang rendah ini berimplikasi pada beban utang yang saban hari kian menunjukkan jumlah yang menaik. Karena itu, tidak mengherankan jika sebagian pihak menyatakan bahwa persoalan anggaran kita bukanlah semata pada kurangnya sisi penerimaan negara, melainkan pada rendahnya kualitas belanja. Fakta ini pula yang menjelaskan neraca APBN kita sepertinya inkongruen dan asimetris. Pada akhirnya, menjadi suatu kewajaran jika wacana pengampunan pajak mendapat resistensi yang meluas.
Dalam APBN 2016, belanja negara telah ditetapkan sebesar Rp2095,7 triliun dengan defisit sebesar Rp273,2 triliun. Dari jumlah ini, sebanyak Rp770,17 triliun atau 36,75 persen dialokasikan untuk dana daerah (dana transfer dan dana desa), dan untuk belanja infrastruktur dianggarkan sebesar Rp313,5 triliun (14 persen belanja). Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen sangat besar untuk pembangunan daerah dan sekaligus pembangunan infrastruktur. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan afirmasi ini, pemerintah berupaya untuk memastikan anggarannya tercapai. Maka itu, kebijakan utang adalah langkah paling rasional dan mungkin untuk ditempuh. Bahkan langkah inipun tidak cukup, sehingga pemerintah lagi-lagi mencoba mencari sumber pendanaan potensial lainnya yang selama ini belum tergarap optimal. Logika faktual inilah yang mendasari ditempuhnya rencana pengampunan pajak.
Namun ternyata, kedua langkah tersebut rupanya memiliki potensi risiko yang tinggi. Kebijakan penambahan utang berdampak pada semakin tertekannya neraca keuangan pemerintah sehingga pembayaran cicilan pokok dan bunga utang ini sudah menjadi pengeluaran wajib pemerintah setiap tahun. Karena kewajiban ini, realokasi pendanaan APBN tidak lagi memiliki fleksibilitas untuk alokasi sektor produktif. Di lain pihak, pengampunan pajak memiliki ongkos psikologis yang sangat mahal. Kebijakan yang sejatinya pemutihan perbuatan melawan hukum ini potensial untuk terjadinya persilangan moral (moral hazard) yang mengurangi kepatuhan terhadap hukum. Jika hal ini terjadi, maka ongkos psikologis ini akan berkembang menjadi ongkos sosial yang merusak ketertiban hukum (law order).
Karena itu, pertanyaan pokoknya: apakah memang APBN kita defisit? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika pemerintah selalu saja mengaitkan kebijakan pengampunan pajak dengan defisit fiskal, sementara pada saat yang sama abai terhadap realitas kinerja belanja pembangunan yang rendah. Padahal setiap variabel ini memiliki relasi kausal dan bersifat resiprokal. Bayangkan misalnya serapan anggaran pembangunan sampai akhir tahun hanya mencapai 70 persen, maka ada 30 persen dari anggaran yang pembiayaannya berasal dari utang. Anggaran yang tidak terserap ini sekaligus menunjukkan inefisiensi dan tidak ekonomisnya siklus APBN kita. Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang kemudian dikembalikan ke kas negara memiliki nilai yang lebih rendah ketimbang jumlah yang kita terima sebelumnya, sebab telah terbebani oleh bunga utang. Pola menahun inilah yang kerapkali kurang disiasati secara optimal.
Dari ilustrasi ini, kita sebenarnya merugi. Hal ini secara langsung berimplikasi pada logika defisit yang seringkali disampaikan pemerintah. Kalau memang kita konsisten menempuh kebijakan anggaran defisit, maka konsekuensi logisnya anggaran akan terserap secara optimal. Postulat ini menjadi klausula baku jika kita tidak ingin menderita kerugian berganda, yakni kualitas pembangunan yang rendah dan beban keuangan yang bertambah. Maka itu, logika fiskal defisit perlu direkonstruksi dengan menekankan pada kualitas belanja. Determinasi ini menjadi sangat perlu agar kita tidak selalu terjebak pada perangkap utang yang kian menggunung. Pada APBN 2016 ini pula beban utang dalam negeri semakin membesar sehingga siklus utang ini akan berimplikasi pada kelangkaan likuiditas, yang ujung-ujungnya mengarah pada perangkap likuiditas (liquidity trap).
Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menetapkan alokasi dana infrastruktur sebesar Rp5500 triliun, dimana APBN hanya mampu mendanai Rp1176 triliun (21,38 persen) saja. Dengan demikian, beban pendanaan sebesar 78 persen mesti ikut ditanggulangi pihak swasta dan BUMN. Besaran angka ini semakin menjelaskan strategi kebijakan defisit yang niscaya dalam kurun lima tahun pemerintahan Jokowi-JK. Maka itu sangat masuk akal pula jika banyak pihak yang mulai meragu beban pembiayaan ini dapat disanggupi dengan kondisi perekonomian yang sedang lesu dan insentif sektor swasta sedang terdegradasi.
Persoalan menjadi kian kompleks ketika ternyata pemerintah dan swasta rebutan utang. Dalam laporan terkini Bank Indonesia (per April 2016), jumlah utang luar negeri swasta mencapai USD164,6 miliar, jauh lebih besar ketimbang utang pemerintah sebesar USD141,79 miliar. Data ini juga menjelaskan bahwa pertumbuhan utang pemerintah mengalami tren menaik yang konsisten. Tren ini mulai terlihat sejak Agustus 2015 (USD 128,78 miliar) yang terus menaik hingga menembus USD141,79 miliar pada Februari 2016. Namun di sisi lain, pertumbuhan utang swasta memiliki votalitas yang cukup tinggi serta tidak memperlihatkan tren yang konsisten. Ini berarti, pemerintah dan swasta akan tetap saling berburu likuiditas.
Disiplin Belanja
Solusi paling rasional adalah meningkatkan kedisiplinan daerah. Oleh karena itu, kementerian dalam negeri harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas belanja. Secara kuantitas, pemerintah pusat harus memastikan daerah merealisasikan rencana anggaran daerahnya masing-masing, terutama sektor prioritas yang memiliki efek pengganda terbesar bagi perekonomian. Peningkatan kuantitas belanja ini menjadi sangat krusial sebagai stimulan bagi aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Setelah itu, pemerintah pusat juga harus memastikan proporsi belanja tersebut tetap sasaran.
Belanja tepat sasaran terjadi ketika belanja bertumpu pada hasil yang ditargetkan. Pada konteks ini, daerah mesti merencanakan anggaran secara optimal dan tepat arah. Jika dalam kenyataannya daerah tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, maka pemerintah pusat dapat membuat skema disinsentif tertentu bagi daerah gagal tersebut. Namun ternyata pemerintah pusat juga belum murumuskan payung hukum ini secara jelas dan terukur. Skema asistensi yang terlihat pada pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) tidak berarti apa-apa jika tidak ditindaklanjuti dengan perangkat sanksi yang lebih tegas yakni pemotongan dana transfer sebagaimana seringkali digaungkan pemerintah pusat.
Tanpa adanya keseriusan untuk menggenjot belanja berkualitas, maka kebijakan fiskal defisit yang berkali-kali dan selalu saja digaungkan pemerintah menjadi kehilangan daya pijak akademik dan empiriknya. Bahkan yang terjadi adalah divergensi pemaknaan atas kebijakan defisit tersebut, yakni bukanlah defisit fiskal yang terjadi, namun fiskal yang sengaja dan niscaya untuk defisit. Kalau sudah begini, defisit fiskal akan berakhir sebagai propaganda belaka.
Arifuddin Hamid
Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi, Universitas Indonesia
*Opini dimuat Harian Jawa Pos, 23 Mei 2016