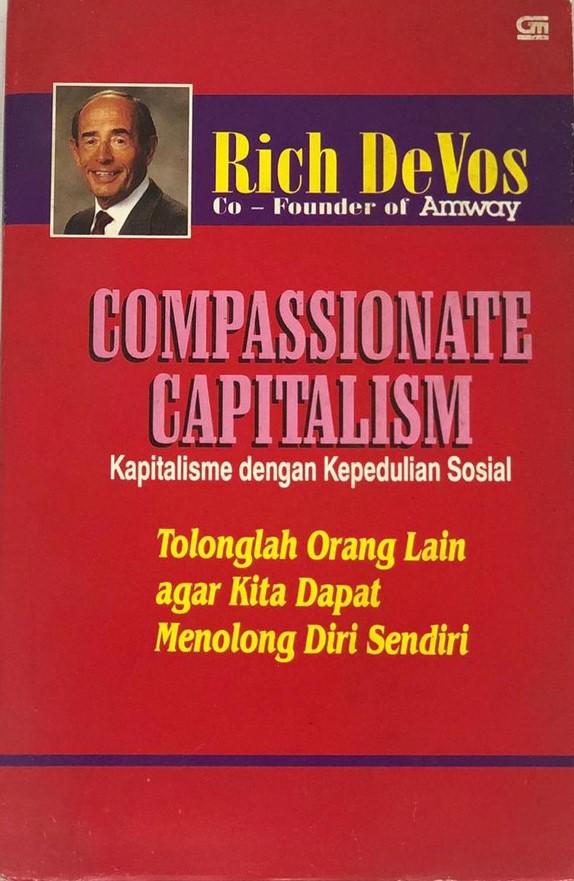Nalar tunggal pembangunan infrastruktur fisik secara masif dan sistemik dalam episentrum kebijakan pembangunan menimbulkan pertanyaan pokok: sampai sejauh mana kebijakan afirmatif ini mencapai titik batas? Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena dua hal: merosotnya kesejahteraan sosial dan terbatasnya ruang fiskal. Dalam kebijakan anggaran pemerintah selama satu dasawarsa terakhir, total alokasi infrastruktur mengalami peningkatan dan laju pertumbuhan yang sangat signifikan.
Paradoks Ganda
Pembangunan infrastruktur ini menampilkan paradoks ganda yang mengalami dilema internal dan eksternal sekaligus. Dari sisi internal kebijakan anggaran, signifikansi alokasi infrastruktur mengorbankan pos belanja aparatur—sektor tertuding sebagai penyebab merosotnya efisiensi ekonomi. Sementara terkait utilitas dan efek pengganda sektoralnya, strategi surplus infrastruktur ini telah memunculkan fenomena “pertumbuhan tanpa pembangunan,” yakni tingkat pertumbuhan tinggi namun minim kualitas kesehatan dan pendidikan (Easterly, 2001). Sebab faktanya, selain karena beban fiskalnya yang sangat berat, strategi pembangunannya juga inkongruen.
Kita sepertinya terjebak amnesia sejarah bahwa selama ini, diluar belanja aparatur, strategi pembangunan Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang bertumpu pada pendanaan sektor infrastruktur. Pos belanja pembangunan yang didanai dari utang luar negeri selama tahun 1967-1998 dalam praktiknya ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, bahkan alokasinya mencapai 40 persen dari total anggaran pembangunan (Hutagalung, 2004: 352). Ini berarti paket kebijakan afirmasi infrastruktur yang sekarang gegap gempita dicanangkan pemerintah sebenarnya bukanlah hal baru, melainkan bentuk repetisi historis.
Menyikapi rekayasa fiskal pemerintah selama hampir lima dasawarsa ini (1967-2016), implikasi teoritik infrastruktur bagi peningkatan kemakmuran masyarakat belum juga mencapai tingkat optimum, bahkan minimalis. Fakta kemiskinan eksplisit menjadi indikator mendasar belum tercapainya tujuan hakiki pembangunan. Kebijakan kejar setoran yang bertumpu pada pendanaan masif infrastruktur mercusuar mobilitas perkotaan dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi potensial mengulang kesalahan lama yang memunculkan fenomena pembangunan semu, yakni pertumbuhan eksklusif dan ketidakmerataan inklusif (Debroy dan Bhandari, 2007).
Strategi pertumbuhan tanpa pembangunan ini tercermin dalam fakta rendahnya kualitas dampak tersebar pembangunan infrastruktur. Meskipun sebagian besar ekonom sepakat dengan urgensitas infrastruktur dalam menunjang industrialisasi, mengukur dampak investasi infrastruktur masih merupakan pertanyaan terbesar sejak lama (Henckel dan McKibbin, 2010). Oleh karenanya, prioritas infrastruktur ini mestinya determinan pada tiga faktor berikut: tingkat pembangunan negara, lama dampaknya bagi pembangunan, dan jenis infrastrukturnya (Estache dan Garsous, 2011). Dengan predikat Indonesia yang masih berkategori negara berkembang, pembangunan sektoral yang tertuju pada industrialisasi mestinya diprioritaskan. Karenanya, infrastruktur mestinya menjadi sarana pengungkit bagi peningkatan produktivitas pertanian dan menjaga keberlanjutan sektor manufaktur. Dengan demikian, diharapkan jenis infrastruktur ini memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang nyata dan sistemik bagi kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Pendanaan infrastruktur ini juga rawan menjadi arena bancakan korupsi. Dari studi empiris yang ada, sebanyak 5-20 persen pembengkakan biaya konstruksi terjadi karena adanya praktik penyuapan (Gulati dan Rao, 2006). Dalam studi mendalam yang dilakukan Olken (2004) terkait konstruksi jalan raya di Indonesia, modus koruptifnya bukanlah pada manipulasi harga namun mendegradasi kuantitas material. Deretan fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tanpa didukung kesiapan mental dan pembentukan moral birokrasi hanya memperluas wilayah penjarahan uang negara. Karenanya tidak aneh jika kualitas iklim investasi kita tidak pernah sehat dan kompetitif.
Dari sisi politik anggaran, studi tersebut menunjukkan paradoks lain terkait strategi kita dalam memperbaiki kualitas pembuat aturan. Dalam APBN 2016, alokasi untuk belanja aparatur menurun cukup signifikan yakni dari Rp.795,5 triliun (60,3% APBN) pada APBNP 2015 menjadi Rp.780,4 triliun (58,3% APBN) pada APBN 2016. Penurunan ini, meskipun kerap diklaim sebagai efisiensi, justru menimbulkan ongkos derivatif berupa hilangnya peluang meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur. Logikanya sederhana yakni dengan alokasi yang begitu besar selama beberapa dekade, kualitas aparatur kita tidak kunjung meningkat optimal. Sementara dengan realokasi yang bertumpu pada pendanaan pembangunan fisik, kita juga belum menyiapkan strategi menyeluruh perbaikan aparatur. Masalah menjadi semakin pelik ketika kebijakan ini nantinya dipandang sebagai penyebab tidak kunjung membaiknya kinerja birokrasi, yang pada ujungnya tidak berkualitasnya peraturan.
Dalam World Development Report (2016), hasil survei Bank Dunia menyangkut indikator kinerja sumber daya birokrasi kita menunjukkan bahwa secara merata kualitas birokrasi kita masih sangat buruk. Dalam hal rekrutmen, lebih dari 50% responden setuju bahwa kementerian sektoral sangat sulit menemukan pegawai berkualitas. Untuk indikator kinerja harian dan tingkat kepercayaan antarinstansi, skornya jauh lebih rendah, yakni sebanyak 75% responden sepakat bahwa kinerja harian birokrasi sangat buruk dan lebih dari 50% kurang percaya dengan pegawai di instansi pemerintah lainnya. Rendahnya kohesivitas sosial dalam birokrasi ini pada ujungnya berdampak menguatnya ego sektoral dan tidak sistematiknya kerja kelembagaan pemerintah.
Dalam laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF, 2015), indeks modal manusia kita masih sangat rendah, yakni hanya berada pada peringkat 69 dari 124 negara. Kita kembali kalah dari negara tetangga terdekat, Filipina berada di urutan ke-46, Malaysia (52), Thailand (57), dan Vietnam (59). Repetisi paradoks ini kembali memunculkan tanya terkait pengaruh kausal investasi pendidikan bagi peningkatan kualitas manusia Indonesia. Untuk kualitas kesehatan, kondisinya juga tidak jauh berbeda. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2015) dalam laporan berkalanya bertajuk “World Health Statistics” embali mencatat bahwa hampir semua kategori sistem kesehatan (jumlah petugas, infrastruktur, dan teknologi kesehatan) masih sangat tertinggal dibandingkan negara-negara kompetitor utama di kawasan. Bahkan untuk komponen kualitas pelayanan kesehatan dan standar untuk hidup, kita masih terkategori negara dengan pembangunan manusia berskala menengah (medium human development), tertinggal ketimbang Singapura dan Brunei Darussalam (berskala sangat tinggi), malaysia dan Thailand (berskala tinggi).
Pada akhirnya, ekses paradoks infrastruktur ini harus disikapi dengan pembentukan demarkasi nilai dan tujuan pembangunan itu sendiri, yakni melalui penajaman tafsir absah pemajuan kesejahteraan umum. Sebab kalau tidak, prioritas realokasi sektoral yang bertumpu pada pendirian instalasi dan konstruksi fisik hanya mengorbankan sektor lain yang sejatinya jauh lebih fundamental dan hakiki untuk dikedepankan, yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Arifuddin Hamid
Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi, Universitas Indonesia
Dimuat Harian Jawa Pos, 1 April 2016