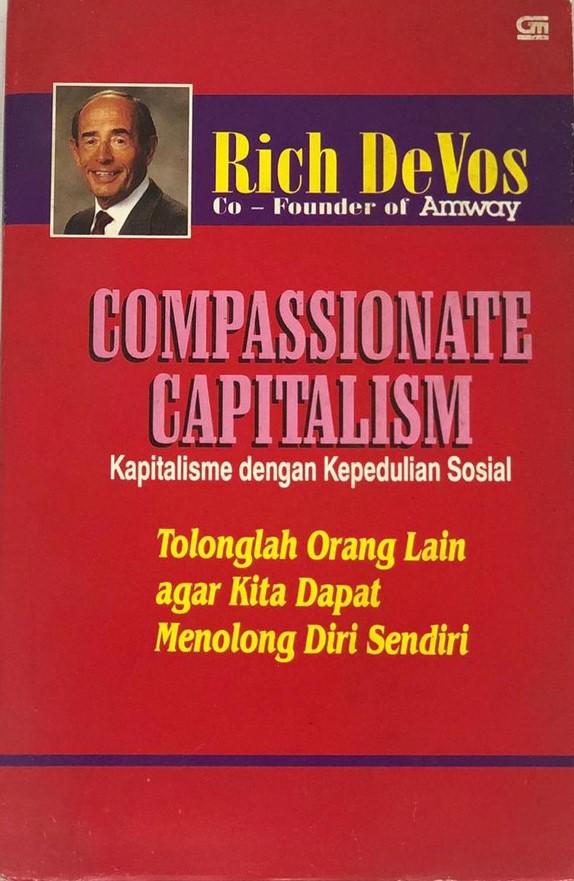Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menegaskan ambang batas Pilpres (presidential threshold) bertentangan dengan UUD 1945 memantik bola salju. Arah perdebatannya menukik, apakah hal serupa mungkin terjadi pada ambang batas parlemen (parliamentary threshold)? Apalagi MK telah memutuskan sebelumnya, bahwa ambang batas parlemen adalah konstitusionalitas bersyarat, yang berarti kewajiban pembentuk UU merumuskan norma yang sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum (Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023). Hal ini juga yang barangkali akan menjadi terma sengit dalam penyusunan RUU Kepemiluan mendatang.
Dilema Ambang Batas
Sebagai bentuk rekayasa elektoral, penentuan ambang batas dipandang sebagai pengingkaran terhadap prinsip proporsionalitas, yang justru membuat pemilu menjadi tidak proporsional. Ada banyak suara yang terbuang, tidak terkonversi menjadi kursi, akhirnya meminggirkan kedaulatan rakyat. Sementara di sisi lain, konsepsi multipartai sederhana yang digadang-gadang pemerintah tidak pernah menjadi nyata. Sistem ini mengalami negasi internal (contradictio in determinis). Jika berkutat hanya pada skema ambang batas, sama artinya kembali terjebak pada stagnasi politik. Alih-alih pemerintahan efektif, regulasi kepemiluan justru akan menyandera efektivitas kerja-kerja pembangunan.
Paska pemilu, beberapa partai dengan kursi terkecil cenderung menjadi bagian dari pemerintah, dengan harapan mendapatkan insentif program dan akses untuk persiapan pemilu berikutnya. Pada 2014, Partai Hanura dengan suara 5,26 persen menjadi bagian dari pemerintah. Di 2019, PPP dengan 4,52 persen suara mengambil jalan yang sama. Ini menandaskan ambang batas justru menjadi sinergi terselubung pemerintah dalam menjaga basis dukungan di lembaga parlemen. Jika pola ini terus dipertahankan, jumlah partai tidak akan pernah mengalami penyusutan optimal.
Hal ini semakin diperparah dengan membengkaknya ongkos politik, yang mengalami hiper-inflasi setiap periode. Dalam simulasi LPEM UI (2014), biaya investasi politik/ dana kampanye yang wajar pada pemilu 2014 berkisar Rp1,18 – 4,6 milyar. Pada 2024, rata-rata biaya politik yang dikeluarkan oleh calon anggota DPR adalah Rp10 miliar (Kompas, 2024). Ini belum termasuk biaya politik uang yang nilainya jauh membengkak. Akses sumber daya dan birokrasi menjadi rebutan partai politik dalam memperbesar peluang politik elektoralnya. Akhirnya, demokrasi menjadi ajang transaksional dan banalitas politik.
Ambang batas juga tidak berdampak pada rekonfigurasi suara dan keterwakilan. Sebab faktanya, partai di Indonesia tidak ada yang mengalami lonjakan suara signifikan. Sepanjang periode paska reformasi, partai terbesar hanya mayoritas minimal, Golkar (21,57 persen) pada 2004, dan Demokrat (20,85 persen) pada 2009. Selebihnya tidak ada yang menembus diatas 20 persen. Volatilitas suara sebuah partai dengan degradasi ekstrim suara partai politik lain tidak teruji. Pada 2009, ambang batas 2,5 persen menempatkan 9 partai lolos DPR. Paradoks terjadi pada 2014 dimana kenaikan ambang batas (3,5 persen) justru meloloskan 10 partai. Pemilu 2019 dan 2024 memang berhasil menurunkan jumlah partai parlemen, namun ini tidak menjawab tujuan awal skema ini. Multipartai sederhana yang diharapkan tidak juga terwujud.
Alokasi Dapil
Daerah pemilihan (Dapil) sesungguhnya wujud alamiah dari ambang batas. Semakin besar alokasi kursi di suatu dapil, maka semakin banyak pula partai yang berhasil menempatkan wakilnya di parlemen, begitu pun sebaliknya. Jika terdapat alokasi kursi maksimal 10 kursi di dapil, maka kemungkinan adanya 10 fraksi juga sangat besar. Hal ini sangat beralasan karena baik sistem konversi kuota (hare quota) sebagaimana yang digunakan pada Pemilu 2014 dan 2009, maupun sistem sainte lague yang diusung pada Pemilu 2024 dan 2019, keduanya sangat ramah pada partai menengah dan kecil. Tidak aneh jika jumlah fraksi di DPR cenderung stabil, dari 9 (2009), 10 (2014), 9 (2019) dan 8 (2024). Tidak ada pengurangan yang signifikan.
Dengan alokasi kursi 3 sampai 12 (2004), maupun 3 sampai 10 (2009 - 2024), jumlah partai di parlemen mengalami stagnasi, atau perubahannya tidak signifikan. Pada Pemilu 2014, dengan 560 kursi tersedia, terdapat 12 dapil yang punya alokasi 10 kursi. Jika setiap partai parlemen mendapatkan masing-masing 1 kursi di 12 dapil ini, maka persentase kursinya sebesar 2,14 persen. Dengan kuota 9 kursi di 10 dapil, setiap penambahan 1 kursi menambah persentase kursi sebesar 1,78 persen. Artinya, dari 22 dapil saja, ada setidaknya 9 partai yang mendapatkan kursi minimal 3,92 persen. Ini sudah cukup untuk lolos ambang batas 3,5 persen pada pemilu 2014. Faktanya, ada 10 partai yang lolos ambang batas.
Pada pemilu 2024, terdapat 580 kursi tersedia dari total 84 dapil. Dapil besar (8-10 kursi) punya alokasi total 38 kursi (6,55 persen dari total kursi parlemen), dengan perincian 11 dapil (10 kursi), 8 dapil (9 kursi), dan 19 dapil (8 kursi). Simulasi sederhana ini menjelaskan bahwa peluang bagi partai parlemen 2024-2029 untuk kembali lolos ambang batas 4 persen pada pemilu 2029 cukup besar. Bahkan, jika ambang batas dinaikkan sebesar 5 persen, 8 partai parlemen, bahkan lebih, akan lolos ambang batas. Jika merujuk pada hasil pemilu tiga periode terakhir, perolehan suara partai parlemen cenderung stabil, kecuali PDIP yang cukup menurun dari 19,33 persen pada 2019 menjadi 16,72 persen pada 2024. Atau Golkar yang menanjak dari 12,31 persen pada 2019 menjadi 15,28 persen pada 2024.
Risiko volatilitas konversi juga tidak relevan. Ketiga fraksi terkecil periode 2024-2029 punya selisih konversi yang kecil: PKS (0,72), PAN (1,05), dan Demokrat (0,13). Jika ketiga partai ini mampu mempertahankan basis suara, maka dapat dipastikan akan kembali lolos parlemen. Hal ini beralasan mengingat setiap periode pemilu suara partai-partai ini cenderung stabil, bahkan punya tren menaik. Deretan fakta inilah yang membuktikan ambang batas tidak efektif dalam menyederhanakan konfigurasi politik di parlemen. Selain banyaknya suara yang hilang dan dituding wujud diskriminasi politik, ambang batas tidak sebangun dengan asa multipartai sederhana.
Padahal, di tengah defisit demokrasi dan menurunnya produktivitas politik, kebaruan ide menjadi sebuah keniscayaan. Relasi asimetris ambang batas dan alokasi dapil ini menjejak kekeliruan dalam pengaturan sistem politik. Atau, bisa jadi, persoalan terbesarnya ada pada pengaturan alokasi dapil yang tidak tepat. Apabila pengaturan mengenai jumlah alokasi kursi di dapil tidak diubah, Pemilu 2029 akan kembali menjadi ritus kuasa dan proseduralistik demokrasi belaka. Kita membutuhkan gagasan segar, berani, dan strategis agar orisinalitas demokrasi presidensial dapat berjalan baik.***
Arifuddin Hamid
Peneliti Prolog Initiatives. Alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia.
Dimuat Hukum Online, 29 Maret 2025.