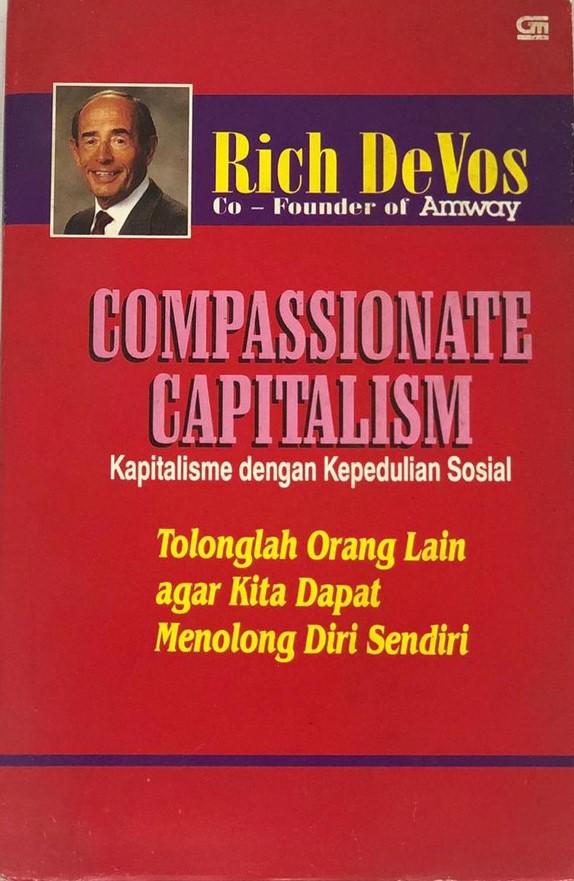Terkuaknya borok Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK II harusnya menjadi titik pijak evaluasi menyeluruh kebijakan afirmasi investasi yang kerapkali meminggirkan hak asasi rakyat. Investasi yang konon menjadi mantra pertumbuhan ternyata membawa eksternalitas negatif yang nyata. Ini semua berawal dari pemaksaan legislasi yang menjadi dasar akselerasi investasi, yang rupanya tidak berwatak manusiawi. Sedari awal pembentukan UU Cipta Kerja menampilkan teatrikal wacana yang sangat gemuruh. Memantik perlawanan komunal, sekaligus menyelip dukungan eksklusif.
UU ini telah menjadikan medan perjuangan hukum terbagi dua, beserta segala alasan pemihakannya. Bagi sebagian kalangan, UU ini kadung dinilai sangat kapitalistik dan cenderung despotik. Sementara untuk yang lain, UU ini dipandang sebagai mantra kemajuan dan pertumbuhan. Investasi dan ekonomi dipacu dengan sebentuk regulasi integratif, klausul campur-aduk yang dibungkus dalam sebuah norma. Oleh karenanya, banyak pihak yang menuding UU ini sebagai aturan sapu jagad, lidinya bercabang sehingga menjangkau satu republik. Sebuah inisiatif yang optimistik, bukan?
Oligarkis
Rupanya, oligarki tidak saja perkara menumpuk sumber daya. Namun juga berkembang jauh menjadi soal pemaksaan ide. Oligarki tidak sebatas pada akumulasi materi, namun juga hegemoni narasi. Sebuah regulasi yang seharusnya dibentuk dengan mengedepankan partisipasi publik yang meluas dipadatkan hanya urusan segelintir kepala. Dalam rangkaian inisiasi sampai pembahasannya, regulasi cipta kerja dibuat dengan cara membunuh garis waktu. Jika partisipasi dituding sebagai skema lambat yang menyabotase pertumbuhan, maka UU Cipta Kerja adalah praktik aktual yang tengah didedahkan para ekonomikus—manusia sebagai makhluk ekonomi. Para ekonomikus ini memandang investasi adalah skema optimum dalam menumbuhkan ekonomi, selain (konon) menciptakan lapangan kerja.
Namun segala rupa eksklusifisme ini pada akhirnya harus tertunduk pada kewibawaan konstitusi. UU Cipta Kerja menyelip kegagalan eksistensial: cacat formil. Maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan legislasi ini inkonstitusional bersyarat. Putusan ini menjadi penguak tabir, ada yang salah dengan cara, metode, dan praktik penyusunan legislasi. Kesalahan ini mungkin akan membuka banyak ranah perdebatan baru soal substansi yang memang sudah dipersoalkan oleh beragam kalangan. Perkara prosedur sudah dinyatakan jelas oleh MK, UU Cipta Kerja terang bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah dapat saja keburu memaksakan kehendaknya, atau rakyat dibungkam. Namun konstitusi adalah pembela akal sehat, persis seperti cacat nyata yang melekat pada legislasi ini.
Legislasi cipta kerja memang menyelip kontroversi berganda. Proses pembentukannya yang meminggirkan demokrasi partisipatoris menjadi watak melekat dari sebuah UU Omnibus. Ia mengatur terlalu banyak perkara, yang bahkan tidak saling berkaitan. Maka pantas jenis legislasi ini seperti gado-gado. Nalar efisiensi dipaksa menjadi pemandu untuk sebuah proses legislasi yang seharusnya demokratis. Peraturan dibentuk seperti sinetron kejar tayang, maka wajar jika menyurat kontroversi. Kondisi ini semakin diperparah dengan siasat pemerintah menerbitkan Perpu 2/2022, yang kemudian menjadi UU 6/2023. Pemerintah seperti sedang melakukan kudeta konstitusional, menegasi perintah MK untuk menegakkan legisme.
Seharusnya pemerintah mematuhi kerangka kerja bernegara. MK berikan perintah memperbaiki dan menggunakan prosedur penyusunan legislasi, bukan justru menafsir subjektivitas penerbitan legislasi darurat dalam ruang hampa. Mengandalkan klausul hal-ihwal kegentingan memaksa dan berlindung dibalik narasi prerogatif adalah bentuk nyata dari keculasan kekuasaan. Cara berpikir ini hanya akan menyisakan preseden dan mewartakan demokrasi berampas. Suara rakyat dan konstitusi lagi-lagi hanya sebatas klaim retorik dalam kehidupan bernegara. Lembaga eksekutif menampilkan wajah hegemonik dan berlaku monopolistik dalam batasan yang paling jauh. Jika sudah begini, apalagi yang tersisa dari demokrasi? Apakah demokrasi telah dibajak sedemikian rupa sehingga berwujud oligarkis?
Dehumanisasi
Investasi dan cipta kerja barangkali diksi yang sangat dialektis. Ia bisa menjadi kausal, tapi mungkin juga akan asimetrik. Investasi yang merakyat akan dapat membentuk lapisan pembangunan, membuka kesempatan kerja. Cara kerjanya partisipatorik dengan melibatkan publik sebagai subjek sekaligus tujuan berinvestasi. Maka untuk negara seperti Indonesia, investasi menjadi salah satu adagium pembangunan yang paling banyak direproduksi kekuasaan. Kapasitas fiskal terbatas sehingga perlu daya dukung masyarakat untuk membantu pemerintah menstimulasi ekonomi dan menuntaskan pengangguran. Namun di sisi lain, investasi juga akan menjadi terma yang menyisakan eksternalitas negatif berganda. Investasi jenis ini akan asimetrik dengan tujuan penciptaan lapangan kerja dan keberlanjutan lingkungan.
Hal inilah yang terlihat dalam kebijakan magis PSN PIK II. Kebijakan afirmasi terselubung ini tentu berawal dari tidak diaturnya pemaknaan strategis dalam UU Cipta Kerja. Bahkan dalam aturan turunannya, baik Perpres 3/2016 maupun perubahan terakhirnya Perpres 109/2020 dan PP 42/2021, indikator strategis ini tidak pernah dirumuskan dalam sebuah norma. Seharusnya untuk kebijakan yang berdampak besar pada kehidupan rakyat, definisi strategis ini dirumuskan bersama oleh pemerintah dan DPR. Karenanya, kebijakan PSN PIK II yang menjadi otoritas mutlak pemerintah adalah ekses nyata dari legisme yang tidak partisipatorik. Padahal, sepanjang 2014 – 2024, terdapat 233 PSN (KPPIP, 2024). Bisa jadi, apa yang terjadi di PSN PIK II adalah fenomena gunung es dari potensi carut-marutnya kebijakan penetapan PSN.
Konsorsium Pembaruan Agraria (2025) mencatat sepanjang 2020-2024, ada 154 ledakan konflik agraria akibat PSN seluas satu juta hektar dan 103 ribu keluarga menjadi korban. Hal ini sejalan dengan besarnya jumlah aduan dugaan pelanggaran HAM dalam PSN sepanjang 2020-2023 sejumlah 114 aduan (Komnas HAM, 2024). Dalam temuan Kontras (2024), terdapat 13 peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada proyek-proyek PSN, baik berupa kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, pengrusakan, okupasi lahan, intimidasi, hingga penganiayaan. Berderet temuan dan laporan tersebut menegaskan PSN tidak sepi masalah, bahkan menjadi dasar dari berbagai konflik dan kekerasan agraria.
Investasi ultraliberal hanya berdampak pada dehumanisasi dan kerusakan lingkungan yang parah. Di satu sisi, banyak korban jiwa berjatuhan akibat kekerasan komunal agraria. Di sisi lain, terjadi laju deforestasi yang sangat parah, tercatat ke-2 terparah di dunia pada 2024 (World Population Review, 2024). Jika ini terus terjadi, PSN seperti teatrikal berdarah dan kekerasan struktural negara. Atau jika ternyata sumbernya dari legisme yang eksesif, maka evaluasi menyeluruh pada substansi legislasi yang mendasarinya, yakni UU Cipta Kerja harus menjadi catatan khusus pemerintah. Ini memerlukan akal sehat dan nurani yang berkeadilan.
Kebijakan obral insentif hanya akan semakin meminggirkan hak kepemilikan rakyat atas kekayaan alam. Kelompok oligarkis sudah terlalu banyak menikmati berbagai kemudahan yang disediakan negara, namun abai pada nasib jutaan rakyatnya. Pengarusutamaan humanisme dan keberlanjutan lingkungan adalah keniscayaan, bukan opsional. Dengan deklarasi HAM sedunia desember tahun lalu yang bertema “Hak-Hak Kita, Masa Depan Kita, Saat Ini,” harusnya pemerintah mampu menjaga harmoni keberagaman menuju Indonesia Emas 2045. Pembiaran, atau bahkan pemihakan pada norma kapitalistik akan mewartakan laku pemerintah yang kontradiksi interminus: mendaku kepentingan rakyat sembari merampas hak konstitusionalnya.***
Arifuddin Hamid
Peneliti Prolog Initiatives. Alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Dimuat Detik, 24 Maret 2025