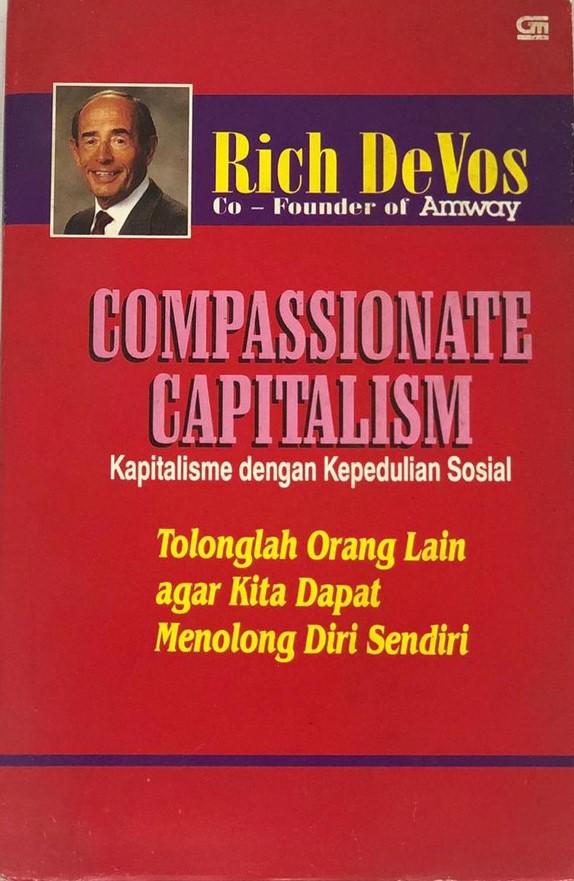Revisi keempat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang telah disahkan pada selasa (18/2) menyisakan kontroversi. Meskipun perguruan tinggi tidak jadi diberikan izin usaha pertambangan, diksi "pemilik manfaat" perlu diatur lebih teknis agar independensi kampus tetap terjaga. Apalagi norma tersebut terkesan diskriminatif, dengan menerapkan standar akreditasi bagi kampus yang akan menjadi pemilik manfaat (Pasal 75A ayat 2). Standar akreditasi ini tak ayal membuat tidak semua kampus mendapatkan dana yang berasal dari pelaku usaha tambang.
Revisi keempat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang telah disahkan pada selasa (18/2) menyisakan kontroversi. Meskipun perguruan tinggi tidak jadi diberikan izin usaha pertambangan, diksi "pemilik manfaat" perlu diatur lebih teknis agar independensi kampus tetap terjaga. Apalagi norma tersebut terkesan diskriminatif, dengan menerapkan standar akreditasi bagi kampus yang akan menjadi pemilik manfaat (Pasal 75A ayat 2). Standar akreditasi ini tak ayal membuat tidak semua kampus mendapatkan dana yang berasal dari pelaku usaha tambang.
Sedari awal, skema pelibatan perguruan tinggi dalam industri tambang memang problematik. Bahkan, lokus persoalannya bukan sebatas perkara anggaran pendidikan, namun tanggung jawab negara. Ini akan berkaitan dengan komitmen negara dalam investasi berkelanjutan sumber daya manusia. Jika negara merasa pendidikan bukanlah prioritas, maka tidak ada kewajiban negara membiayai pendidikan. Namun pendidikan adalah amanat konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ini berarti, pendanaan pendidikan oleh negara bersifat wajib (mandatory spending). Negara tidak sekadar fasilitator, atau regulator. Negara mesti berperan aktif dalam memastikan dana pendidikan tercukupi. Inilah esensi dari konsep negara kesejahteraan. Rumusan pasal dalam revisi UU Minerba tersebut mengesankan lepas tangan negara dalam pendanaan pendidikan dan pengembangan riset.
Korporatisasi tidak Langsung
Pelibatan secara langsung perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang adalah bentuk nyata dari korporatisasi pendidikan. Kampus berubah menjadi korporasi yang bertujuan mengejar keuntungan. Apalagi, industri pertambangan sangat rawan melanggar etika lingkungan, mengancam hak-hak masyarakat adat, konflik agraria, serta beresiko tinggi secara ekonomi. Masalahnya kian rumit ketika kampus dibebankan tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya pengabdian kepada masyarakat.
Potensi konflik yang muncul antara pelaku usaha tambang dengan masyarakat dan lingkungan justru akan mencederai semangat tridharma. Secara historis, kampus bahkan menjadi benteng moral. Moralitas publik tercermin dalam sikap kritis kampus dalam menghela kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Ini meniscayakan independensi dan imparsialitas kampus.
Skema pemilik manfaat adalah korporatisasi yang tidak langsung. Meskipun kampus bukan pelaku usaha, skema ini tetap mengancam kemerdekaan sikap perguruan tinggi. Jika sebagian dari keuntungan bisnis perusahaan tambang dialihkan menjadi kekayaan kampus, maka ada relasi kuasa yang terbentuk. Ini akan menjadikan kampus bergantung dari pendanaan pelaku usaha tambang. Kebergantungan ini menjadi problematik: relasi kelembagaan dan asal usul dana.
Terminologi pemilik manfaat sebenarnya dikenal dalam kepustakaan hukum dan diatur dalam hukum di Indonesia. Dalam Perpres 13/2018, pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan organ korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.
Pasal 4 ayat (1a) Perpres 13/2018 juga menetapkan bahwa pemilik manfaat dari korporasi memiliki saham lebih dari 25 persen yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilik manfaat adalah orang-perseorangan yang memiliki saham di perusahaan. Adopsi terminologi pemilik manfaat (beneficial owner) ini sebenarnya dalam rangka mencegah maraknya praktik pencucian uang dan pidana terorisme.
Jika merujuk pada Pasal 75A ayat (1) revisi UU Minerba tersebut, tujuan pemerintah pusat memberikan wilayah izin usaha prioritas kepada korporasi adalah untuk kepentingan perguruan tinggi. Norma ini memantik pertanyaan lanjutan, apakah korporasi prioritas tersebut berafilisasi dengan kampus? Jika terjadi perjanjian kerjasama dalam rangka pembagian sebagian keuntungan (ayat 3), bagaimana memetakan kampus yang layak mendapatkan pendanaan?
Akreditasi adalah standar baku dengan tujuan klasifikasi dan standardisasi kampus di Indonesia. Lalu, dari 4523 kampus (PDDikti, 2023), ada berapa banyak perjanjian kerjasama dengan korporasi prioritas? Ada berapa banyak perusahaan yang diberikan prioritas? Atau jika hanya sebagian kampus yang dipilih, apakah ini tidak akan menimbulkan peta konflik dan diskriminasi? Beragam pertanyaan ini tentu relevan di benak publik. Jika benar terminologi pemilik manfaat itu sebagaimana diatur dalam Perpres 13/2018, maka kampus adalah pemilik sebenarnya dari korporasi prioritas tersebut.
Di sisi lain, asal-usul dana juga perlu menjadi catatan khusus. Perusahaan tambang yang mendapatkan keuntungan dari perusakan lingkungan dan konflik agraria, apakah memenuhi standar moral dan etika dalam pendanaan pendidikan? Yayasan Auriga Nusantara, misalnya, mencatat terjadi deforestasi yang parah pada 2024 seluas 261 ribu hektar, dan sebanyak 38 ribu hektar atau 14,7 persen karena konsesi tambang.
Di sisi lain, letupan konflik agraria karena pertambangan mencapai 41 kasus di sepanjang tahun 2024 (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2025). Deretan fakta ini menegaskan industri pertambangan adalah industri yang berlumuran masalah. Jika kampus harus bergantung pada kebaikan hati perusahaan tambang, sama halnya melegitimasi ekspansi pertambangan yang merusak.
Kebijakan Bermasalah
Korporatisasi perguruan tinggi, baik yang langsung menjadi pelaku usaha, maupun yang tidak langsung berupa pemilik manfaat, adalah kebijakan bermasalah. Kebijakan ini menjadi bukti lepasnya tanggung jawab negara dalam pendanaan pendidikan. Pemerintah rupanya keliru tafsir dalam menjalankan amanat konstitusi. Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 menegaskan Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika dunia kampus adalah episentrum pengembangan riset, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah mendanainya.
Pengalihan kewajiban dari Pemerintah ke korporasi, apalagi korporasi tambang, hanya akan merawat oligarki. Ini adalah bentuk nyata dari pembungkaman demokrasi dan kebebasan akademik. Relasi kuasa sebagai ekses dari pemberian dana pendidikan ini menjadikan kampus tidak lagi menjadi institusi sipil yang kritis. Kampus tidak lagi mewakili moralitas publik. Jika ini terjadi, senjakala demokrasi mulai semakin nyata. Pemerintah telah berlaku hegemonik.
Padahal, demokrasi dan pertumbuhan memiliki kesenyawaan. Melalui kebebasan berekspresi, pemilu yang bersih, dan pembatasan kekuasaan, demokrasi (liberal) punya efek permanen terhadap pertumbuhan jangka panjang (Schlosser dan Eberhardt, 2023). Cara terbaik bagi pemerintah dalam menjaga demokrasi dan konstitusi, serta menembus pertumbuhan 8 persen, adalah dengan kesetimbangan peran.
Kewajiban pemerintah memastikan pengembangan riset melaju kencang. Ini adalah perintah konstitusi yang eksplisit dan tegas. Tugas institusi sipil menjadi penjaga moralitas publik. Korporasi ikut mengelola kekayaan alam negara yang hasilnya menjadi penerimaan negara. Pemerintah melakukan fungsi alokasi dengan pendanaan perguruan tinggi. Semua berperan dengan proporsional.
Pada akhirnya, demokrasi tetap terjaga. Pertumbuhan juga tercapai. Semoga.
Arifuddin Hamid
Direktur Eksekutif Prolog Initiatives. Alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Dimuat Antara, 15 April 2025